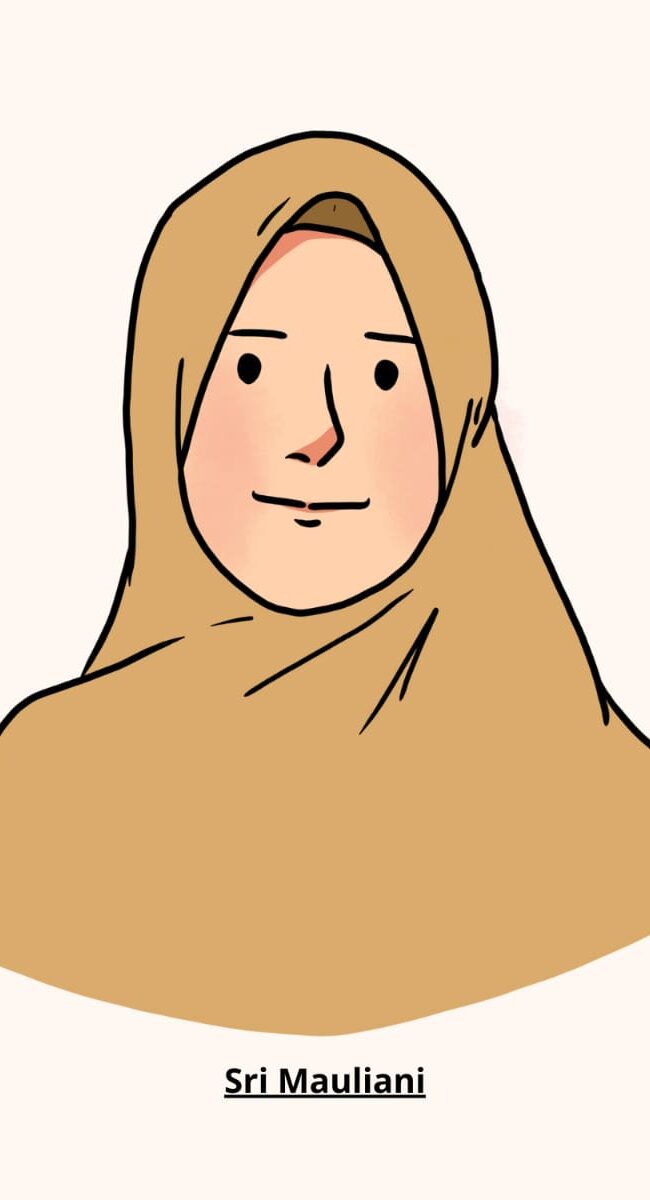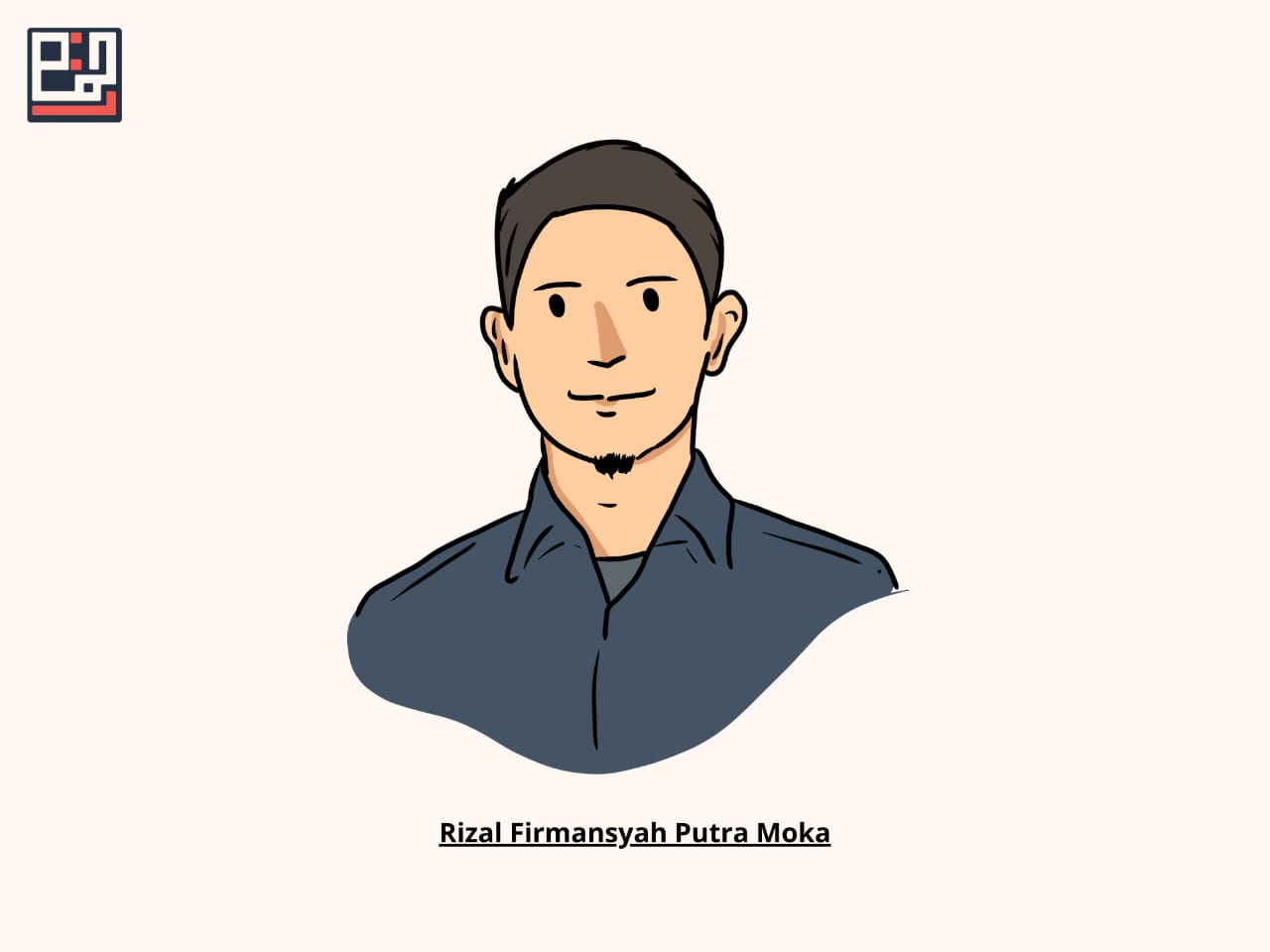
Konflik Tambang dan Krisis Iklim
“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 11)
Paradigma nifaq atau hipokrit sebagaimana yang disinggung oleh ayat di atas tercermin dalam proyek pembangunan negeri ini. Tambang merupakan topik yang tak akan pernah habis untuk dibahas, lantaran telah menjadi komoditas dan kendaraan bagi kekuasaan di musim Pilkada. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat, ada 11 konflik tambang sepanjang tahun 2019 dan meningkat drastis pada tahun 2020 sebanyak 45 konflik. Dari sekian banyak konflik tersebut, hingga tahun 2020 terdapat 3.092 lubang bekas galian tambang yang ditinggalkan oleh perusahaan tanpa reklamasi. Lubang tambang itu menyebar di beberapa daerah di antaranya Riau, Sumatera, Banten, Lampung dan paling banyak ditemukan di calon Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur sebanyak 1.735 lubang. Akibatnya 24 orang meninggal lantaran jatuh ke dalam lubang tersebut.[1]
Keterkaitan antara perusahaan dan elit penguasa menjadi salah satu faktor masalah ini sulit untuk diredam. Elit penguasa bahkan di beberapa kesempatan secara terang-terangan menjadi pelindung bagi perusahaan mengatas namakan kepentingan umum, atau bahkan jika elit penguasa sendiri adalah pelaku usaha tambang maka ia cenderung akan melakukan defend dari bahaya yang mengancam eksistensinya dengan berlindung di balik teks UU ITE sebagaimana yang baru-baru terjadi pada kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan salah seorang menteri Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan.
Di antara perusahaan yang dilindungi oleh elit penguasa dengan UU minerba misalnya PT Kendilo Coal Indonesia; Kaltim Prima Coal/KPC; PT Multi Harapan Utama; Arutmin; PT Adaro Indonesia; PT Kideco Jaya Agung; dan PT Berau Coal.[2]
Batu Bara, Sumber Listrik
Kita semua tahu bahwa batu bara menyumbang emisi karbon paling banyak dan merusak lingkungan. Selain itu, ketergantungan pada energi fosil juga berdampak serius pada kelangsungan hidup manusia. Angka kematian akibat polusi udara mencapai 450.000 jiwa pada 2018 dan diperkirakan dapat bertambah menjadi 650.000 jiwa pada 2040.[3] Sayangnya, dampak bagi manusia dan lingkungan seolah tidak berarti jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh, tentu bagi mereka yang disebut dengan oligarki. Konon kabarnya, batu bara adalah sumber energi yang paling murah untuk kebutuhan listrik; sehingga pemerintah menjadikannya sebagai prioritas dibandingkan dengan sumber energi lainnya.
Sejak zaman orde baru, pemerintah menggandeng swasta untuk mengatasi defisit pasokan listrik dengan menerapkan skema take or pay (TOP). Skema TOP berarti pemerintah wajib membeli listrik yang disediakan oleh swasta dalam jumlah tertentu berdasarkan kesepakatan di awal dalam kondisi apa pun. Laporan keuangan PLN mencatat di tahun 2018 ada 277 pembangkit listrik swasta yang menjalin kerja sama dengan PLN.[4] Akibatnya, terjadi kelebihan pasokan listrik atau oversupplay dan pemerintah dituntut untuk terus membeli listrik dari swasta yang berdampak pada kerugian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Angka kelebihan pasokan ini tidak main-main, Direktur Utama PLN menyebut tambahan permintaan (demand) hanya 800 megawatt (MW); sedangkan total pasokan listrik sebanyak 600 gigawatt (GW), artinya kelebihan pasokan sebanyak 500 GW.[5] Rakyat ujung-ujungnya harus menanggung beban dari masalah ini. Anggaran subsidi listrik sebesar Rp 61,53 triliun di tahun 2021 harus dipotong 8,13% menjadi Rp 56,5 triliun untuk tahun 2022.[6]
Krisis Iklim
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa batu bara menghabiskan ongkos lingkungan yang tidak sedikit. David Wallace—wells dalam bukunya bumi yang tak dapat di huni dengan sangat apik merangkum fenomena alam yang bersinggungan dengan aktivitas manusia. “Panas maut”, demikian keterangan pada salah satu judul sub bab yang membuat saya cukup tercengang sehingga menghabiskan waktu semalaman untuk tidak terlelap. Pertama, David mengenalkan sebuah istilah wet-bulb temperature atau “suhu bola basah” dalam terjemahan bahasa Indonesianya, untuk mengukur suhu. Dilanjutkan dengan penjelasan bahwa rata-rata suhu bola basah sebagian besar daerah di dunia maksimum 26 atau 27 derajat Celsius dengan batas atas 35 derajat. Lebih dari itu, manusia akan mati kepanasan, kondisi ini oleh David disebut dengan heat stress atau “stress panas”.[7]
Pada tahun 2015, di India dan Pakistan terjadi gelombang panas yang menewaskan ribuan orang. Suhu panas di India mencapai angka 48 derajat Celsius dan menyumbang angka kematian tahunan 0,75 persen. Hal yang sama terjadi di Eropa pada tahun 2003 menewaskan 2.000 orang per hari. Demikian pula di Rusia pada tahun 2010, menewaskan 55.000 orang. Skenario terburuk yang diramalkan oleh Ethan Coffel suhu ini bisa meningkat 100 bahkan 250 kali lipat pada tahun 2080.[8]
Membaca ulasan David tersebut, mulanya saya sedikit tidak percaya seolah tengah membaca sains-fiksi di negeri antah berantah yang tak perlu untuk ditanggapi serius. Setelah meraih ponsel dan bertanya pada mesin pencarian, sebuah teknologi mutakhir abad ini; ternyata memang benar adanya bencana yang dikisahkan oleh David. Anda mungkin berpikir bahwa itu adalah ulasan bencana luar negeri, sedangkan kita di Indonesia berada dalam zona aman. Litbang Kompas baru-baru ini merilis kajian terkait fenomena cuaca ekstrem di Jakarta berupa panas dahsyat di siang hari dan beralih cepat menjadi badai hujan disertai angin kencang menjelang sore. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta bahkan selama dua pekan terakhir di April 2022 mengeluarkan peringatan cuaca ekstrem secara berkala, mulai dari banjir; angin kencang; hujan lebat; hingga pohon tumbang.
Diketahui bahwa salah satu penyebab dari masalah tersebut adalah Urban Heat Island (UHI) atau pulau panas perkotaan; yakni kondisi di mana suhu wilayah pusat kota yang jauh lebih panas dibandingkan dengan area sekitarnya. Fenomena UHI terjadi lantaran luasnya area terbangun, meningkatnya emisi dari moda transportasi dan minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Di Jakarta, RTH bahkan kurang dari 10%, padahal dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTH paling sedikit 30% di wilayah kota.[9]
Perjanjian Paris
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), sebuah organisasi internasional yang menampung para ilmuwan di seluruh dunia meneliti tentang perubahan iklim akibat aktivitas manusia merilis laporan ke enam bahwa emisi gas rumah kaca sebelum tahun 2030 harus dikurangi 43% dan mencapai netralitas karbon di tahun 2050.
Merespons kajian IPCC tersebut, dalam Paris Agreement (PA) dibuatlah komitmen negara-negara dunia untuk menurunkan emisi karbon dan gas rumah kaca serta memastikan suhu global tidak naik lebih dari 2˚C (3.6˚F) dan menjaga kenaikan suhu global tetap di bawah 1.5˚C (2.7˚F). Indonesia sebagai salah satu negara yang turut serta dalam PA kemudian menyatakan sanggup menurunkan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia 2021. Meski demikian, beberapa pihak menilai bahwa Komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon belum optimal bahkan ada langkah pemerintah yang dirasa tidak tepat. Institute for Essential Services Reform (IESR) misalnya mengkritisi kebijakan pemerintah yang kemudian dimasukkan ke dalam rekomendasi kebijakan. Ada beberapa poin yang menjadi catatan penting, satu di antara poin rekomendasi kebijakan tersebut adalah berkaitan dengan paradoks kebijakan pemerintah yang masih mengistimewakan PLTU di samping Perjanjian Paris menurunkan emisi karbon.[10]
“Tingginya intermitensi energi terbangkitkan dari pembangkit listrik tenaga energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Bayu; karena variabilitas sumbernya yang dapat menyebabkan terganggunya stabilitas sistem menjadi pembenaran bahwa pembangkit termal, khususnya PLTU, menjadi tumpuan dalam mendorong ketersediaan listrik dan menjaga kestabilan sistem; tanpa mempertimbangkan skenario dalam penggunaan teknologi lainnya. Asumsi ini tidak tepat karena saat ini sudah banyak tersedia teknologi untuk mengatasi tantangan intermitensi ini tanpa menghasilkan emisi, seperti pumped hydro, baterai, compressed air storage, dan sebagainya. Teknologi-teknologi energi yang tersedia saat ini dapat digunakan untuk mencapai dekarbonisasi 2050.”
Catatan di atas ternyata disadari sepenuhnya oleh David sehingga turut memberikan komentar bahwa ada campur tangan politik di dalamnya. Kepentingan oligarki tentu menjadi prioritas dari kebijakan, sehingga pertanyaan menohok yang dilontarkan oleh David di tengah sub bahasan “panas maut” adalah; “Akan sepanas apa jadinya ?, Pertanyaan itu boleh jadi terdengar saintifik, mengundang kepakaran, tapi jawabannya hampir sepenuh-nya manusiawi- dengan kata lain, politis.”
[1] Andita Rahma “JATAM Nasional Catat ada 45 Konflik Tambang Sepanjang 2020”, (Tempo 24 Januari 2021) https://nasional.tempo.co/read/1426234/jatam-nasional-catat-ada-45-konflik-tambang-sepanjang-2020
[2] Eko Prasetyo, Corona, Oligarki, dan Orang-orang miskin: Zaman Otoriter (Yogyakarta: UMY Press, 2020), hlm. 59
[3] Ibid, 61
[4] Ibid, hlm. 62
[5] Achmad Dwi Afriyadi, “PLN Lagi Kebanjiran Pasokan Listrik, Dirut: OverSupply yang Luar Biasa”, (DetikFinance, 23 Februari 2022) https://finance.detik.com/energi/d-5955457/pln-lagi-kebanjiran-pasokan-listrik-dirut-oversupply-yang-luar-biasa
[6] Anisarul Umah, “Waduh! Gara-gara Skema TOP Listrik Ini, APBN Tekor Terus” (CNBC, 9 September 2021) https://www.cnbcindonesia.com/news/20210909134815-4-274963/waduh-gara-gara-skema-top-listrik-ini-apbn-tekor-terus
[7] David Wallace—wells, Bumi yang Tak Dapat Dihuni; The Uninhabitable Earth (Jakarta: PT. Gramedia, Jakarta, 2020) hlm. 42
[8] Ibid, 43-44
[9] Yosep Budianto, “Mewaspadai Perubahan Cuaca Ekstrem Wilayah Perkotaan”, (Kompas, 16 April 2022) https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/04/15/mewaspadai-perubahan-cuaca-ekstrem-wilayah-perkotaan
[10]Geny Jati, “Simak 6 Perbedaan pada NDC Indonesia Tahun 2015 dan NDC Hasil Pemutakhiran 2021”, (IESR, 6 Oktober 2021) https://iesr.or.id/simak-6-perbedaan-pada-ndc-indonesia-tahun-2015-dan-ndc-hasil-pemutakhiran-2021