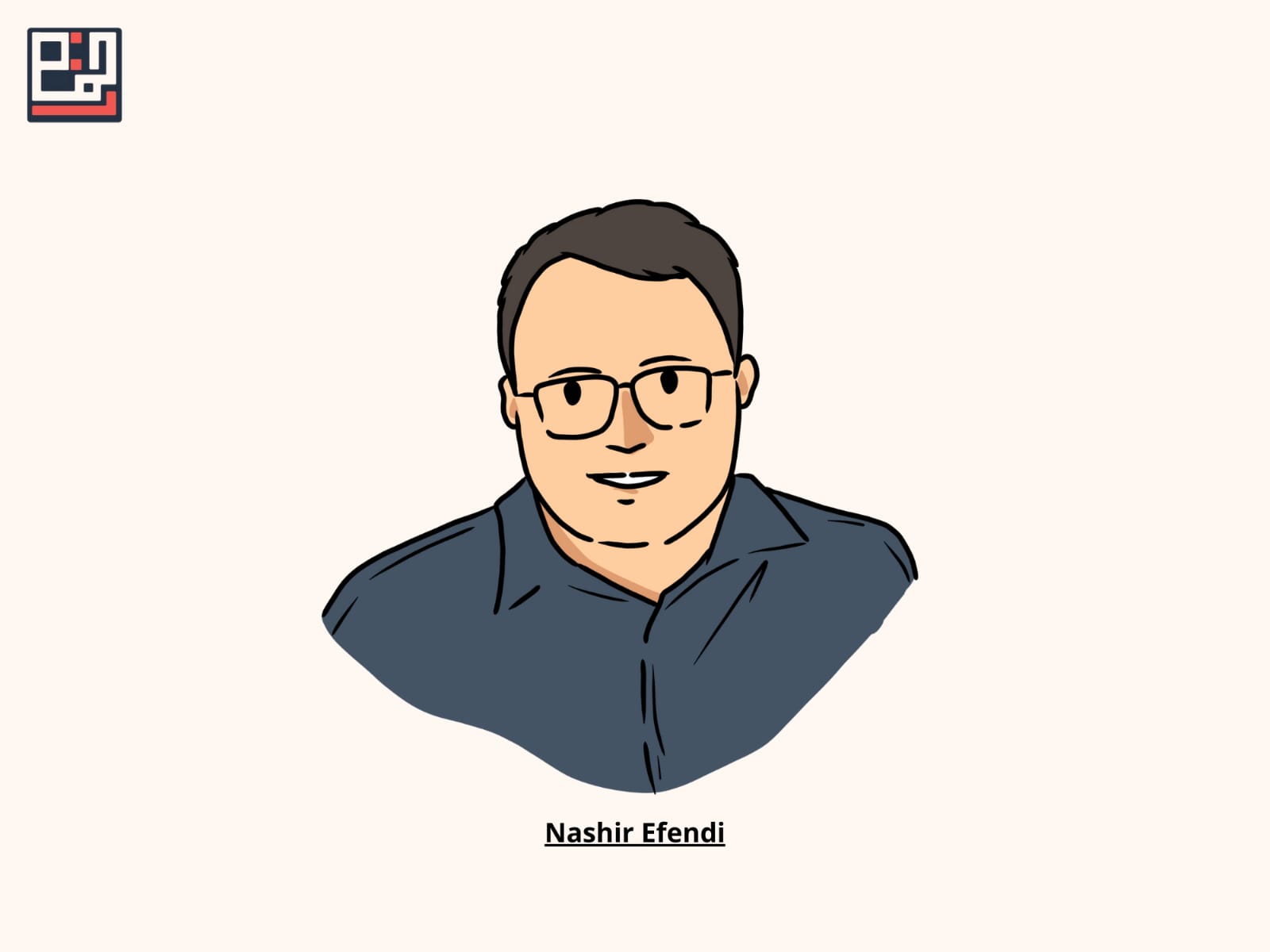
Memaknai Ulang Fenomena Ghosting
Akhir-akhir ini kita mengenal aplikasi terkenal di media sosial seperti Tinder di satu sisi menjadi angin segar bagi para penganut aliran jamaah Singlelillah. Ingin memiliki pasangan yang seperti apa? Stylish-kah? Good looking-kah? Aplikasi itu bisa membantu seseorang untuk menemukan tipe pasangan yang diharapkan, minimal yang dapat dilihat dari kasat mata — secara fisik.
Jika ada seseorang yang lihai menata komunikasi atau retorika yang asik dan menyenangkan, ia berpotensi untuk melanjutkan pertemuan dengan lawan jenis yang memiliki kecocokan atau frekuensi ke dalam dunia nyata serta membuat komitmen hubungan yang lebih dalam. Lantas apa yang terjadi jika tiada angin tiada hujan sosok yang sudah terlanjur merasuk ke dalam ulu hati tersebut pergi tanpa pamit?
Fenomena ghosting ini menjadi konsekuensi yang mestinya disadari kala menggunakan beragam jenis media sosial. Pada awal 2021 di Indonesia, kita sering melihat fenomena ghosting sebagai hal yang perlu disoroti setelah polemik artis muda terkenal Felicia Tissue vis a vis Kaesang Pangarep.
Perasaan Felicia yang digambarkan hancur sempat menjadi trending Twitter, lantaran Kaesang menautkan hatinya pada wanita lain. Gosipan macam ini dapat diterima khalayak karena mampu membuka berbagai kisah dan perasaan sama yang kiranya dialami banyak netizen.
Permasalahan semacam ini mengajak kita tertuju pada satu pertanyaan; Bagaimana posisi realitas dunia maya yang disodorkan internet dapat mengundang pengalaman emosional seseorang? Pertanyaan ini muncul sekaligus akan menguji apakah sebuah konstruksi yang dibangun bahwa pasangan yang pergi tiba-tiba layaknya ‘hantu’ itu dapat divalidasi? Apabila seseorang meyakini sedang mengidap ghosting; saya pikir hal itu menunjukkan arogansi psikologis dalam menafsirkan diri sebagai makhluk yang ‘nyata’.
*
Berbicara mengenai konsep ghosting sebenarnya bukanlah hal baru, bahkan bagi seorang filsuf Perancis, Rene Descartes. Pada gagasan yang terkenalnya, Cogito Ergo Sum, menurutnya, realitas yang notabene menjadi dasar utama diskursus ghosting adalah hal yang subjektif. Bahwa benda yang dilihat secara seseorang secara indrawi pada dasarnya tidak berdiri sebagai realitas yang bisa ada tanpa kehadiran diri seseorang itu. Segala benda di dunia ini pasti ada yang mencipta, memindahkan, menyentuh, merubah dan sebagainya.
Sebaliknya, Descartes menduga segala benda mampu mempengaruhi yang seorang yakini keberadaan bersama sifatnya karena benda-benda tersebut adalah hasil olah citra dan persepsinya. Pendek kata, sebuah benda dapat dinyatakan ‘nyata’ karena kesadaran serta pikirannya yang tengah bekerja.
Pada satu sisi, pemahaman yang masih mentah dapat membuat seseorang berada dalam situasi solipsistik; bahwa ia adalah satu-satunya entitas di dunia yang berposisi sebagai realitas sesungguhnya. Adapun benda di luar dirinya tidak lebih dari kreasi fantasi. Peristiwa ini karenanya masuk akal untuk mendudukkan seseorang pada kondisi yang dialami pengidap skizofrenia.
Tetapi Descartes memang bukan bermaksud membawa manusia pada tahapan psikologis melalui konseptualisasi tersebut. Usaha Descartes untuk menjauhkan persoalan itu adalah dengan melanjutkan; bahwa kendati sebuah benda ada disebabkan oleh persepsi manusia, kita bukan penyebab aktif dari konstruksi benda tersebut.
Benda lain yang pada akhirnya ditemukan sebenarnya telah meluas dalam ruang dan waktu. Persepsi manusia lebih jauh diletakkan Descartes sebagai alat subjektif untuk mengetahui benda dan alam semesta sebagai hal yang bukan sekadar ‘ada’ secara konsep; tetapi akhirnya ‘nyata’ secara materiil-bersama dengan sifatnya.
*
Sejenak kita dapat merefleksikan kisah para penyintas ghosting saat bergumul dengan ketidakberuntungannya. Begitu romansa dan intensi yang tengah dirasakan akhirnya tidak berbanding lurus dengan loyalitas dan eksistensi; dapat kembali terlihat ada kesan dari mereka untuk mengkampanyekan diri sebagai ‘makhluk nyata’ ‘yang masih ada’.
Indikasi ini diambil dari fenomena yang meyakinkan bahwa pasangan-pasangan ‘berlari’ dan ‘menghilang’ dari realitas asmara yang sedang tersusun rapi sebelumnya-begitulah sebagaimana kita mengetahui ghosting per definisi. Namun mari berpikir sejenak jikalau para penyintas ghosting, secara sadar atau tidak, agaknya merupakan sekelompok Cartesian garis keras; apa yang nyata bagi mereka adalah apa yang selamanya berada dalam jangkauan indera serta pikiran terkininya.
Pada konklusi tersebut, bukan berarti penulis berniat untuk menghina atau membuang rasa simpati terhadap para penyintas ghosting. Namun kiranya sebelum lebih jauh untuk mengafirmasi konsep ‘ghosting’, kita perlu memikiran ceramah Parmenides, yang bahkan telah lama bernyawa sebelum Descartes.
Katanya, sesuatu yang ada tidak mungkin tidak pernah ada. Terlepas manusia yang akhirnya mengasumsikan bahwa sesuatu itu sekarang tidak ada, hal itu disebabkan karena manusia yang ikut membawa sesuatu itu ke dalam pergerakannya. Pergerakan tersebut sifatnya semu, karena ia selalu mengatur segala benda yang tertarik untuk ikut berubah. Jika ditafsirkan lebih jelas lagi; Parmenides ingin membuat reminder bahwa semua benda adalah ada sekaligus nyata di masanya masing-masing, entah itu di masa lampau, masa kini atau masa depan.
Karenanya, ghosting kiranya ialah sebuah bentuk kecacatan konseptual tentang realitas. Yang semestinya harus dipahami adalah seorang mantan kekasih sebenarnya saat ini tengah menggoreskan sejarah dalam lembar kehidupan. Dalam arti yang lebih sederhana, seseorang tersebut pernah singgah atau menetap dalam hidup dan nyata sebagai masa lalu.
*
Lalu, mengapa konsep tersebut bisa terdistorsi sampai menghadirkan fenomena ghosting? Hal ini dapat disebut sebagai konsekuensi dari materialisasi dan objektifikasi perasaan. Realitas dalam hubungan yang semu, misalnya, dibentuk oleh internet. Realitas semu tersebut secara kasat mata tampak lebih seksi hingga mampu mewujudkan kehendak yang memiliki kecenderungan eksesif.
Bentuk logika tersebut kurang lebih seperti ini: jika penulis sedang mencintai lawan jenisnya, maka dia yang telah meraih perhatian dan rasa cinta penulis semestinya harus selalu ada secara nyata bersama penulis. Persoalan seperti ini sama persis dengan konsep yang dibentuk oleh Descartes di atas; bahwa benda akan dikatakan ‘ada’ selama ia telah berhasil dipersepsikan melalui indera. Bagi penulis, hal itu adalah akibat konsekuensi logis dari gagasan Descartes, bahwa manusia sebagai objek yang berpikir terpisah dengan objek secara luas yang tidak memiliki jiwa dan pikiran.
Yang membuat bahaya adalah dengan membenarkan persepsi inderawi sebagai gerbang utama perihal yang ‘nyata’-manusia bisa terperangkap pada asumsi yang menafikkan apa yang semestinya memang nyata dalam kehidupan. Bagaimana jika ‘objek nyata’ itu tiba-tiba tak terjangkau indera, objek tersebut sangat mungkin untuk kembali pada predikatnya yang abstrak/tidak nyata.
Pada akhirnya, kita semestinya paham jika mengafirmasi bahkan terpaku pada ghosting sebetulnya adalah upaya untuk memaksakan kehendak status realitas seseorang di masa lalu agar selalu abadi-takkan lekang oleh waktu. Kecuali, jika tidak lupa dengan arahan dari Parmenides. Padahal tentu saja batas dari manusia ialah sampai pada taraf mempersepsikan, bukan justry mengabadikan. Dengannya, yang hendak penulis mencoba memahami ulang ghosting yang seakan-akan merupakan saat di mana manusia kehilangan peluang untuk bisa menjadi makhluk yang mempersepsikan sesuatu sebagaimana mestinya.
*
Tentu saja ghosting adalah hasil akhir dari persepsi manusia yang sistemik untuk menarasikan kisah cinta yang terhempas. Tapi lebih jauh daripada itu, ghosting dapat menyadarkan keangkuhan diri manusia ketika melihat subjek lain sebagai benda yang tak bernyawa; bila tidak sesuai ekspektasi, sosok subjek lain bisa menjadi sasaran empuk untuk menghancurkan kehadirannya.
Di waktu yang sama, manusia juga mampu menghargai eksistensi manusia yang lain sebagai subjek yang sama-sama berpikir-terlepas dari manusia yang meninggalkan tanpa sebab pasangannya begitu saja adalah aktor antagonis dalam setiap romansa. Tapi bagaimanapun juga, kalau kata sahabat saya, dunia dan seisinya bukan hanya tentang “si dia” saja.
Apakah sebagai subjek yang memiliki kuasa dalam tubuh dan jiwa kita masing-masing; kita mau selamanya dibelenggu oleh kuasa sesosok subjek lain karena pengalaman yang dimasukkan ke diri kita? Lebih dalam, sepertinya mendengarkan lagu dari Andra Respati & Elsa Pitaloka berjudul Korban Perasaan adalah pilihan tepat. Mengapa lagu ini? Nikmati saja bait-bait liriknya, pesan dan maknanya.
*
Ketua Bidang Perkaderan PW IPM Jawa Timur.





