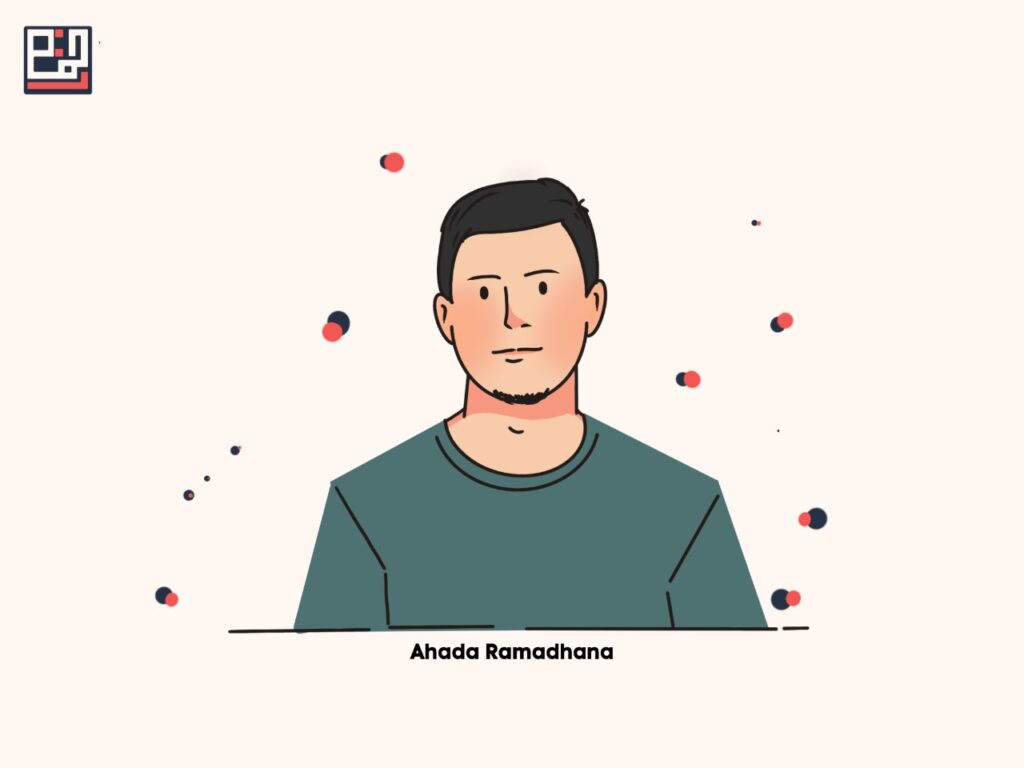Resensi Buku “Serba-Serbi Pengasuhan Anak”
Penulis: Devi Delia dan Emeldah Suwandi
Penerbit: Elex Media Komputindo, November 2021
Tebal: xiv+158 Halaman
Saat mencoba memanggil memori tentang momen kelahiran anak kami, saya tak bisa mendefinisikan secara pasti bagaimana perasaan saya ketika baru sah jadi ayah. Yang bisa saya ingat, perasaan saya didominasi kecemasan akan tanggung jawab orang tua pada anak, diimbuhi rasa belum percaya sepenuhnya bahwa saya sudah punya momongan.
Kala si kecil lahir sekira 3 tahun lalu, usia pernikahan kami belum genap setahun. Yang saya khawatirkan sebenarnya bukan cuma “tidakkah kami terlalu tergesa punya anak?”, tapi juga “apakah kami—khususnya saya—sudah siap jadi orangtua?“
Bagaimanapun kerisauan itu tak kunjung lesap, saya tak mungkin begitu saja mencerabut diri dari kenyataan. Sembari ‘bertumbuh kembang’ bersama anak, saya menemukan buku Serba-Serbi Pengasuhan Anak di sebuah marketplace. Saya tertarik memiliki buku ini karena napas utamanya bersumber dari problem pengasuhan yang paling kerap dihadapi para orangtua.
Devi Delia dan Emeldah Suwandi, berbasis ilmu dan pengalaman selaku psikolog klinis, memetakan 8 tema besar yang jadi keluhan utama seputar pengasuhan anak, hasil interaksi mereka dengan pasien. Kedua penulis, yang sama-sama alumnus magister psikologi, membabar soal disiplin, tantrum, sulit fokus, speech delay, pola asuh digital, parental burnout, konflik, co-parenting.
Buku ini jadi pedoman khususnya bagi orangtua baru seperti saya yang sering merasa butuh arahan dalam memenuhi hak-hak anak. Dengan bahasan luas dan dalam, buku ini melengkapi ilmu parenting ala medsos yang umumnya ikhtisar ringkas belaka. Buku ini tak cuma menuntun para orangtua merespons berbagai perilaku anak lewat tips praktis, tapi juga mengajak orang tua membangun pemahaman dan prinsip fundamental seputar pengasuhan anak.
Bab pembuka, soal disiplin, menyorot persepsi keliru bahwa kedisipilinan anak bisa hadir sendiri. Sebelum lebih jauh, kita perlu sepakati dulu untuk memakai definisi disiplin dalam buku ini—yang mengacu Kamus Oxford—yakni melatih/membimbing anak bernalar dan berperilaku. Buku ini mengkritik para orang tua yang menganggap perilaku tertentu dari anak kecil wajar ditoleransi, tapi saat anak agak besar dituntut paham konsep disiplin dengan sendirinya. Padahal, anak butuh dibimbing untuk memahami mana perilaku yang baik dan mana yang buruk.
Menurut buku ini, waktu terbaik memulai disiplin adalah sedini mungkin, karena hal ini butuh proses dan konsistensi, tak bisa sekejap. Sebaliknya, menoleransi perilaku anak dengan dalih ‘wajar masih kecil’ sama saja membolehkan anak mengulangi proses belajar yang salah.
Sikap memaklumi kekeliruan anak bukanlah hal baru dan jauh dari keseharian. Pernah suatu kali istri saya menyaksikan sendiri, balita tetangga mendorong-dorong anak batita kami. Jangankan minta maaf, si ibu yang mendampingi balitanya cuma diam dan tak mendidik apa-apa pada anaknya.
Tampaknya salah kaprah itu sudah membudaya. Anak berbuat salah karena belum paham, bukannya diberi tahu malah dimaklumi. Bagaimana anak bisa paham benar-salah/baik-buruk jika tak ada yang mendidik.
Di bab disiplin, buku ini juga mengulas seputar hukuman. Apa pun jenis hukuman, baik verbal (disalahkan, dimarahi) ataupun fisik (dipukul, dicubit), tergolong disiplin yang keliru. Selain cuma efektif sekali (tak untuk seterusnya), hukuman melahirkan anggapan menyakiti orang tak papa asal tujuannya baik. Hukuman juga membuat anak tak respek dan membuat jarak dengan orangtua, serta mendorong kepatuhan yang berorientasi sekadar menghindari hukuman bukan atas kesadaran. (Hal 8-12)
Kasus pokok di dunia anak yang diulas berikutnya ialah tantrum, yakni luapan emosi (misal marah, kecewa) tak terkontrol di waktu dan tempat yang tak seharusnya. Alasan anak sering ‘berulah’, termasuk tantrum, bisa jadi sebagai cara instan dapat perhatian dan dituruti kemauannya. Penyebab lain tantrum bisa karena ketidaknyamanan fisik (capek, lapar, sakit) atau ada konflik internal karena keterbatasan kemampuan menghalangi keinginannya yang mulai beragam. (Hal 21-25)
Menghadapi anak tantrum, penulis menyarankan agar memberi anak pemahaman logis, singkat, dan jelas (karena penjelasan panjang sulit dipahami anak) terkait biang tantrum. Misalnya kita melarang minum es karena apa, sebab anak punya hak dapat penjelasan. Penulis juga menekankan, tantrum adalah momen wajar dalam perkembangan anak, karena kemampuan mereka mengelola emosi masih terbatas. Jika masih sulit dikontrol maka beri waktu, yang jelas orangtua harus memastikan tantrumnya tidak membahayakan dirinya maupun orang sekitar.
Bab tak kalah penting adalah parental burnout, yakni lelah fisik dan mental (kewalahan) dalam proses pengasuhan, yang dampaknya tak cuma ke anak tapi juga hubungan pernikahan. Tak ketinggalan, buku ini memberi sejumlah tips mengelola burnout (hal 100-105).
Pertama, me time. Tips ini berangkat dari anggapan “tak bisa memberi kenyamanan pada anak jika diri sendiri belum dalam kondisi nyaman”. Maka jangan tak enak hati mengambil me time, sebab hal itu adalah kebutuhan mendinginkan perasaan.
Kedua, kelola perasaan. Sebagai orang tua wajar lelah dan marah, tapi perlu mengontrolnya jangan sampai diluapkan di saat tak tepat. Diam sejenak bisa jadi pilihan untuk ‘menormalkan’ emosi, supaya bisa bersikap responsif bukan reaktif.
“Semua emosi pada dasarnya boleh Anda rasakan. Emosi bukanlah sesuatu yang punya label baik/buruk. Setiap emosi memiliki fungsinya masing-masing. Emosi adalah peringatan bahwa tubuh sedang mengatakan sesuatu pada diri kita. Termasuk perasaan cemas dan marah yang sedang Anda rasakan.” (Hal 102)
Ketiga, komunikasi. Perlu diskusi berkelanjutan soal pola asuh karena tumbuh kembang anak adalah tanggung jawab bersama. Tak cuma dengan pasangan, tapi semua yang terlibat pengasuhan termasuk orang tua/mertua dan babysitter.
Keempat, hindari melabeli/menyalahkan diri. Dorongan dalam diri untuk memberi yang terbaik pada anak, di titik tertentu bisa menjadi beban. Saat kecolongan, misal anak sakit atau perkembangan anak lambat di aspek tertentu, kita merasa jadi orangtua buruk. Jika begitu, kita perlu mengevaluasi perasaan maupun pembagian porsi asuh.
***
Meminjam istilah Helmy Yahya, isi buku ini “daging semua”. Jika ditarik benang merah, bahasan tiap bab mesti meliputi ciri, penyebab, dampak, dan tips. Separuh awal buku ini berfokus bagaimana menangani anak, sedangkan separuh akhirnya tentang manajerial sebagai pasangan dan orangtua.
Karena disusun oleh dua penulis, perlu penyesuaian berbeda saat membaca 4 bab awal dan 4 bab akhir. Meski ditulis terpisah, duo penulis memastikan tak ada pengulangan sub-bahasan.
Di empat bab awal, rujukannya mayoritas diparafrasa dan bahasanya lebih ngepop dengan diksi yang lebih meng-Indonesia. Penulis tak ragu memakai kalimat langsung dengan tuturan sehari-hari tanpa menggunakan kata-kata baku.
Sedangkan empat bab akhir tampak upaya mengenalkan banyaknya istilah misal fatherless (absennya ayah dalam tumbuh kembang anak), postpartum blues (gangguan psikologis usai persalinan), technoference (interupsi teknologi yang memengaruhi emosi anak) serta upaya menyebut sumber secara terang meski ada footnote, jadi terasa lebih akademis. Di separuh akhir juga kental memakai sudut pandang istri ketimbang sebagai kesatuan pasangan.
Pekerja media daring, ayah satu anak