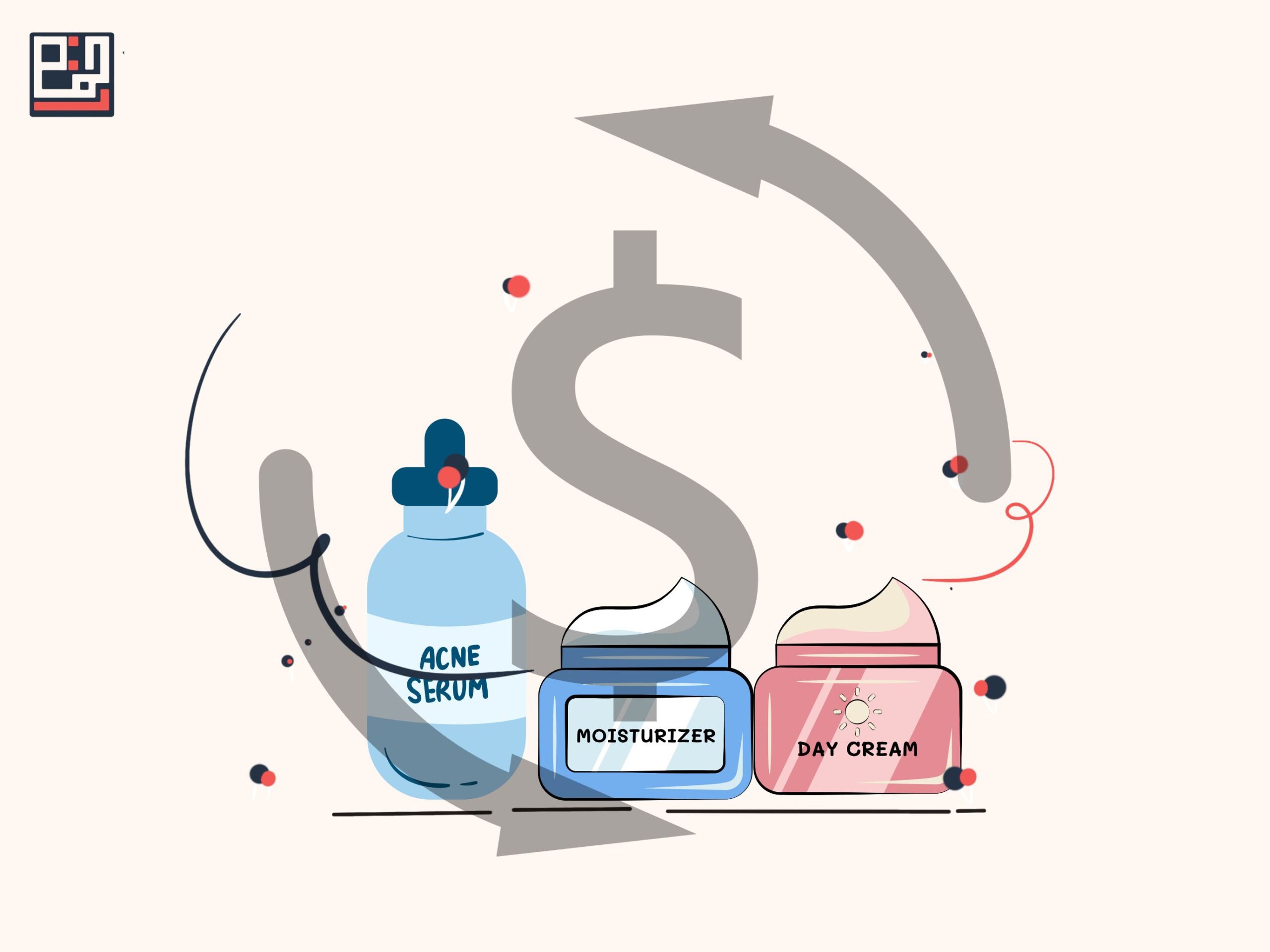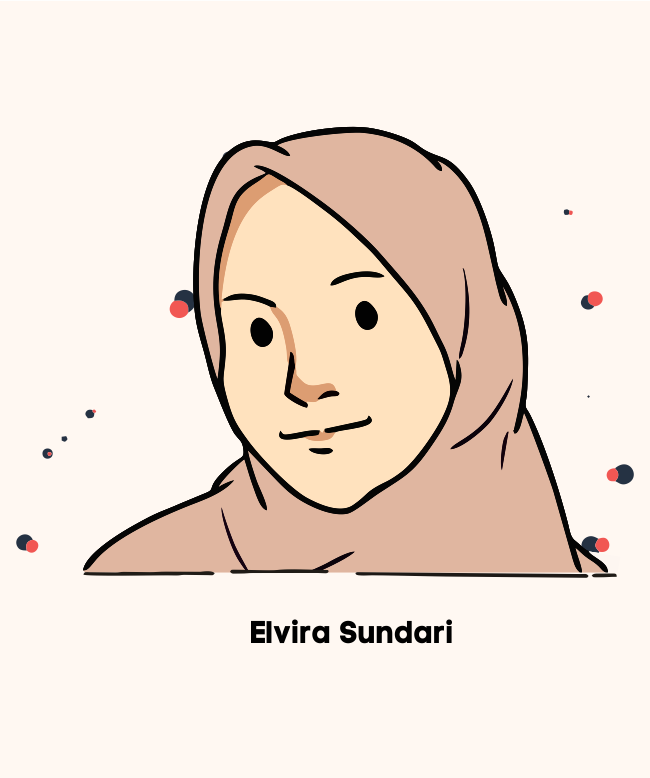Saya Bercengkrama dengan Istri Tentang Islam dan Perempuan
“Kanda, aku pengen nanya sesuatu,” istri saya beringsut mendekati saya malam itu. Saya sedang makan bakso di lantai, di kamar kami yang mungil, dan ia mulanya sedang sekrol-sekrol instagram di kasur. Dari gelagat dan raut wajahnya, sepertinya ia pusing sehabis melihat salah satu posan―dan tidak bersepakat.
Benar saja. Saya melongok, melihat layar ponsel yang ia sodorkan. Ada semacam akun hijrah yang memuat hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ath-Thabrani. “Nikahilah wanita yang subur dan penyayang,” sabda Nabi, dalam posan itu. “Sebab, dengan jumlah kalian yang banyak, aku akan berbangga di hadapan para Nabi di hari kiamat kelak.”
Saya langsung paham situasi. “Apa yang Dinda pusingin?”
“Ada, nggak, makna lain dari hadis ini?”
“Ada, emang kenapa?”
“Apa memang perempuan harus beranak banyak? Mereka yang secara fisik nggak bisa beranak, gimana? Nggak semua perempuan itu subur, Kanda. Bayangin perasaan mereka waktu membaca hadis ini disebar-sebar di Instagram tanpa penjelasan bijak. Terus, kenapa umat itu harus kuantitas?”
Istri saya menyemburkan banyak pertanyaan. Saya … saya tetap mengunyah bakso dan tidak terpengaruh. Setelah satu dua suapan yang ditunggui istri saya dengan muka tidak sabar (seharusnya dia bersabar, masa cuma saya yang harus bersabar?), saya letakkan sendok. Sengaja saya bersendawa dulu supaya istri saya makin jengkel menunggu.
“Ada profesor, muslim, mengajar di Kanada, Kanda lupa nama kampusnya. Dia tinggal di pinggiran yang rata-rata penduduknya peternak sapi. Suatu hari rekan-rekannya mampir ke rumah, mau makan malam. Satu rekannya nyeletuk: ‘di pemukiman ini kamu, kan, minoritas. Kenapa tidak tinggal di daerah A yang warga muslimnya cukup banyak’? Sejenak, profesor itu melihat sekeliling. ‘Bicara apa kamu? Lihat sapi-sapi itu, di sini saya mayoritas’.”
Saya ceritakan itu panjang lebar dan istri saya kelihatan tidak paham. “Maksudnya gimana?”
“Maksudnya, umat yang banyak dalam hadis itu tidak mesti manusia bentuknya. Al-Qur’an bilang, tiada hewan melata atau burung yang beterbangan di udara melainkan semuanya bagian dari umat. Jadi, perbanyak umat itu maksudnya: lakukanlah konservasi! Hewan-hewan jangan dibunuh. Biodiversitas harus dijaga.”
Sekarang ia heran. “Aku tahu hewan itu umat, tapi ayat ini konteksnya pernikahan, Kanda.”
“Oh, iya juga, sih.”
Sedetik kemudian istri saya sadar kalau tadi saya tidak serius. Mukanya menggelembung. Saya tertawa karena berhasil ngalor-ngidul dan membuatnya jengkel. Menghubung-hubungkan sesuatu yang tidak nyambung memang merupakan keahlian saya. Saya hendak kembali pada bakso saya yang enak itu, tapi tangannya menahanku. “Ayo serius, Kanda. Aku serius ini.”
“Ya, ya, ayo serius.”
“Sejak baca Muhammad-nya Martin Lings,” istri saya menunjuk buku babon berwarna putih yang tergeletak di kasur, “aku merasa suatu hadis harus dijelaskan oleh hadis yang lain. Aku ngerasa hadis di akun ini juga begitu.”
“Memang begitu, Dinda. Hadis memang tidak bisa berdiri sendiri. Pikiran dan kehendak Nabi ndak bisa dinilai dari satu hadis. Apalagi kebanyakan hadis dikutip dengan sistem quotes. Coba perhatikan hadis di akun itu. Audiens hadis itu siapa? Nabi sedang ngobrol dengan siapa dan berapa lama? Anggaplah obrolan aslinya berlangsung 15 menit, kenapa yang dikutip hanya kalimat yang kalau dilafalkan cuma butuh sekitar 10 detik?”
Istri saya mencerna.
“Karena yang memukau bagi si pendengar hanya di bagian itu. Maka kemungkinan, konteks hadis itu tersembunyi di 15 menit yang tidak dikutip. Kalau konteksnya hilang, susah. Hadis menjadi penggalan-penggalan yang maknanya tidak rasional dan tidak manusiawi. Kadang malah terkesan memojokkan perempuan. Seolah-olah Islam dibangun dari kepentingan laki-laki, untuk kesenangan versi laki-laki.”
“Terus, konteksnya bagaimana?”
Saya jelaskan bahwa hadis yang ia bingungkan terdiri atas dua bagian. Pertama, kalimat nikahilah wanita yang subur dan penyayang, yang dalam pandangan saya merupakan washilah atau cara. Kedua, kalimat sebab aku akan bangga dengan jumlah umatku yang banyak, yang dalam pandangan saya merupakan ghayah atau tujuan.
“Inti dari hadis ini ada di ghayah, Dinda. Washilah-nya ndak wajib, hanya motivasi. Orang Arab sejak dulu memang suka sama perempuan subur dan anak yang banyak. Lelaki Arab merasa di situlah harga diri mereka berada. Tapi, menjadikan istri anak sebagai barang, kan, ndak baik. Jadi, lihatlah tujuannya. Sebetulnya Nabi sedang meluruskan niat orang Arab. Seakan Nabi bilang: boleh kamu perbanyak anak, tapi karena akhirat, bukan gengsi sosial.”
“Kenapa harus dipisah-pisah jadi washilah dan ghayah?” Tanya istri saya lagi, dan saya mulai merasa kritisismenya itu membuat kehangatan dan rasa bakso saya sebentar lagi akan memudar.
“Masa iya washilah-nya cuma satu? Tidak. Kita bisa memperbanyak umat dengan jalan hidayah, converting. Kita sebarkan pemikiran, kita perbanyak kebaikan. Siapa tahu orang tersentuh dan masuk Islam. Coba lihat, Imam Nawawi menjomblo sampai wafat. Beliau memilih washilah sebagai ulama yang fokus sama ilmu. Pemikiran beliau memperkuat umat, memperkuat dakwah. Jadi, memisahkan washilah dan ghayah sudah jadi tradisi ulama.”
Tampaknya istri saya masih kurang puas, jadi saya tambah lagi penjelasannya―sambil melirik bakso saya yang mulai kembah.
“Di surat Taha, Allah bilang: “Dirikanlah salat untuk mengingatku.” Dirikan salat itu washilah, untuk mengingatku itu ghayah. Salat memang menjadi washilah yang wajib, tapi ia bukan satu-satunya cara untuk mengingat Allah. Sebab di Ali Imran, Allah bilang: mereka yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring.Ayat itu bukan tentang salat, tapi tentang zikir yang aktual, yang bisa di mana saja dan kapan saja.”
Setelah lama termenung, istri saya tersenyum. “Makasih, Kanda.”
“Yo.”
Saya lanjut makan bakso. Sudah saya duga, cita rasanya berubah.
Kami bercengkrama hingga larut. Kami sama-sama menyayangkan penolakan Muhammadiyah atas rancangan Permendikbud Ristek no. 30 Tahun 2021. Bukan argumen Muhammadiyah yang kami sayangkan (kami paham keyakinan Muhammadiyah untuk menyelaraskan nilai agama di tiap kebijakan publik), melainkan pada kenapa penolakan itu yang bersuara adalah lelaki, yang sangat mungkin tidak pekat-lekat menggeluti kasus KS di dunia pendidikan.
Rasanya, di balik argumen Muhammadiyah ada semacam keluguan dan ketidaktahuan tentang bagaimana ratusan ribu kasus KS selalu tersandung oleh patriarki dan membikin korban serta advokat menjadi sangat frustasi. Tapi, dalam hati, saya juga meragukan produk hukum akan membantu korban mendapatkan keadilan. Masalah kita bukan di tiadanya produk hukum, melainkan struktur kuasa yang melindungi pelaku. Bagaimana melawannya?
Dalam kasus-kasus yang mencerminkan ketidak-adilan semacam ini, kita tidak boleh naif bahwa lawan kita seringkali adalah mereka yang punya modal sosial-ekonomi, yang cukup mengerikan bila dipakai untuk mengancam, menekan dan menjatuhkan. Mestinya Muhammadiyah fokus menyingkirkan struktur kuasa yang serba-mungkar ini dari kampus-kampusnya. Ya, kampus-kampus Muhammadiyah tidak bebas dari maraknya kasus KS. []
Direktur eksekutif RGST (The Reading Group for the Social Transformation), peneliti di JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah), peneliti di Komunitas Riset “Akademi Gajah”.