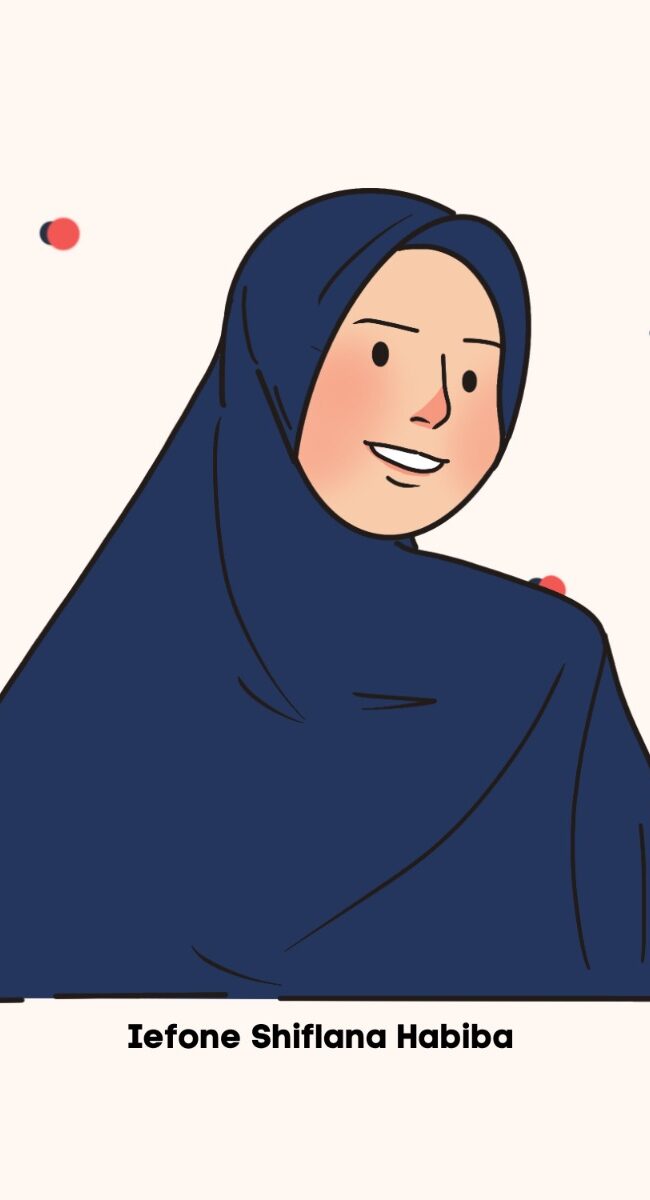Kaderisasi Politik dalam Keluarga
Kajian politik kerap dikaitkan dengan persoalan keluarga. Terlebih, jika kekuasaan tampak “diturunkan” atau “diwariskan”. Sementara itu, kita hidup di negara yang mengklaim dirinya demokratis. Menurut sebagian analis politik, ada praktik yang tak lazim: politik dinasti. Bahkan secara lebih lugas, Kanchan Chandra dalam “Democratic Dynasties” (2016) menamai hal ini dengan istilah “dinasti demokratis”. Sungguh istilah yang penuh paradoks.
Kendati demikian, praktik tersebut benar-benar ada. Tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga negara-negara lainnya di dunia. Dalam berbagai kontestasi politik praktis, jabatan politik seorang suami kerap digantikan isterinya pada periode berikutnya. Bahkan anak-anak atau kerabatnya yang lain. Sebagian mantan kepala daerah mempraktikkan hal ini.
Politik Dinasti
Dalam konteks Indonesia, Joko Widodo, mantan Walikota Solo yang saat ini menjabat sebagai Presiden, mengupayakan posisi terpenting di kota tersebut kepada Gibran Rakabuming, putera pertamanya. Sementara menantunya (suami dari anak kedua Presiden, Kahiyang Ayu), Bobby Nasution, mencoba berkarir di jalur yang serupa: menjadi Walikota Medan.
Bukan rahasia lagi jika seorang petinggi partai kemudian mewariskan posisinya kepada anaknya. Dalam konteks PDIP, Megawati hendak menurunkan kepada puteri tercintanya, Puan Maharani. Demikian pula dengan Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono tampak bangga dan bahagia digantikan Agus Harimurti Yudhoyono.
Betapapun hal-hal tersebut dianggap sebagai politik dinasti, sebenarnya peran keluarga begitu besar ketika mengupayakan proses literasi politik. Seorang kepala keluarga dianggap telah berhasil memperkenalkan hobi (politik) atau hal yang ditekuninya kepada anak-anaknya. Bahkan mereka tampaknya sukses membuat putera-puterinya terampil dalam bermanuver politik.
Mimpi-mimpi besar ditanamkan. Permainan siasat yang menarik, juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sang anak. “Nanti kalau jadi pemimpin, kita akan memperjuangkan kehidupan rakyat.” Meskipun, entah rakyat yang mana yang diperjuangkan.
Itu semua yang terjadi dalam proses literasi politik keluarga, yang tentu tidak didapatkan oleh bahkan para mahasiswa doktoral ilmu politik. Pengalaman langsung oleh mentor “praktisi” yang ambisius, menjadikan proses kaderisasi begitu efektif. Siapa saja yang ditempa sebagai agensi politik kekuasaan, kemungkinan besar akan “jadi”.
Bagi para pecinta realpolitik, pendidikan politik dalam keluarga yang berhasil adalah hal yang membanggakan. Bagi analis, hal itu adalah fakta obyektif yang memperkaya khazanah terutama tentang perilaku politik. Kemudian, bagi orang-orang partai yang tidak mendapatkan posisi strategis, tentu keberhasilan itu adalah hal yang membuat iri. Bagi para pejuang demokrasi, itu semua adalah aib berbangsa dan bernegara.
Berbagai respon yang beragam atas fenomena politik dinasti, sebenarnya tergantung kepada posisi dan sudut pandang yang dimiliki. Apakah dinasti politik mengancam demokrasi? Mungkin saja iya, karena praktik ini melanggengkan kekuasaan dengan cita rasa monarkis (turun-temurun).
Modal Politik
Namun, apakah literasi dan kaderisasi politik yang sungguh-sungguh akan menghasilkan para pemain politik yang handal? Sepertinya begitu. Hanya saja, proses yang lebih detil harus diamati secara seksama. Misalnya apakah modal sosial dan ekonomi menjadi instrumen yang penting dalam proses pendidikan politik? Seberapa penting? Mengapa?
Kita bisa dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan melihat apa yang terjadi pada Sandiaga Uno, Erik Tohir, Airlangga Hartarto, Nadiem Makarim, Luhut Binsar Panjaitan dan lainnya. Mereka hebat, dikenal masyarakat luas dan jelas sekali, kaya raya.
Ketika kekuasaan politik sekaligus memastikan kepemilikan modal sosial dan ekonomi, maka agaknya proses kaderisasi ini sulit diterapkan oleh orang biasa. Jelas tidak semua orang biasa (bukan pejabat) memiliki modal sosial dan ekonomi. Sebaliknya, mereka yang genap dengan keduanya, belum tentu memiliki hasrat untuk berkontestasi politik praktis.
Pengecualian berlaku bagi mereka yang tidak memiliki modal ekonomi, tapi kharismanya begitu kuat di tengah masyarakat. Modal sosial inilah yang menjadi mesin pendorong bagi mereka untuk menggapai jalan politik tertentu. Para tokoh agama atau pimpinan aktivis, biasanya meniti karir melalui jalur ini.
KH Ma’ruf Amin yang sinar kharismanya terang, kini menduduki jabatan Wakil Presiden. Berturut-turut, Muhadjir Effendy (Menko PMK) dan Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama) adalah aktivis Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sosok seperti Mahfud MD (Menko Polhukam) juga termasuk di antara para tokoh berpengaruh.
Memang secara teoretik, demokrasi yang substansial cenderung mengabaikan kepemilikan modal ekonomi sebagai sumber kekuatan dalam kontestasi politik praktis. Sebagaimana kredo yang dijunjungnya, “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” adalah ekspresi demokrasi dalam merayakan nilai penting kemerdekaan yang beradab (civil liberty).
Jadi, sebagaimana yang ditekankan David Avrom Bell (2020), seorang sejarawan politik dari Universitas Princeton Amerika Serikat, bahwa sumber kekuatan yang ideal adalah modal sosial: gagasan cerdas dan masuk akal, kesungguhan dan pengalaman membangun masyarakat, serta citra diri yang tampak sempurna (kharisma).
Kaderisasi Politik
Kaderisasi politik dalam keluarga, mestinya berpijak kepada pembangunan sumberdaya manusia yang memihak demokrasi substansial. Yakni mengedepankan penempaan modal sosial, bukan modal ekonomi.
Kenyataannya saat ini, setiap kontestasi politik praktis menjadi ajang pertarungan antar pemilik modal ekonomi. Siapa yang punya modal paling banyak, maka dialah yang memiliki kans paling besar untuk menang. Tidak heran dengan demikian, hanya para konglomerat yang mengendalikan pertarungan ini. Di samping itu, modus operandi-nya masih sama: jual beli suara antara rakyat dan calon pejabat. Dengan demikian, seperti yang selama ini diamati oleh Indonesianis terkemuka, Marcus Mietzner (2013), demokrasi yang berjalan bersifat transaksional.
Memang kaderisasi politik dalam keluarga yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi substansial tidak menjanjikan kemenangan dalam perlombaan realpolitik. Tapi ketika banyak negarawan (atau katakanlah para aktor politik) saat ini kemudian membuat trend kaderisasi politik “yang baik” maka akan menumbuhkan harapan lahirnya para negarawan yang hebat dan jauh dari tradisi transaksional, pragmatisme yang sempit dan terjerat jebakan keserakahan.
Nah, musim politik elektoral akan bergulir pada 2024 nanti. Dan setiap lima tahun sekali, hal ini akan diulang selayaknya hajatan rutin anak-anak bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah, siapkah kita memulai permainan politik yang lebih baik?
Para mentor politik dalam keluarga, harus memulai proses kaderisasi politik yang kelak memproduksi para pemimpin yang pro-demokrasi substansial. Jika pemimpin sekedar hasil dari “menang-menangan” modal ekonomi dan manuver dengan segala cara, maka sebenarnya kita sendirilah yang mengekalkan politik yang destruktif.[]
Dosen UMM dan Direktur Riset RBC Institute A. Malik Fadjar