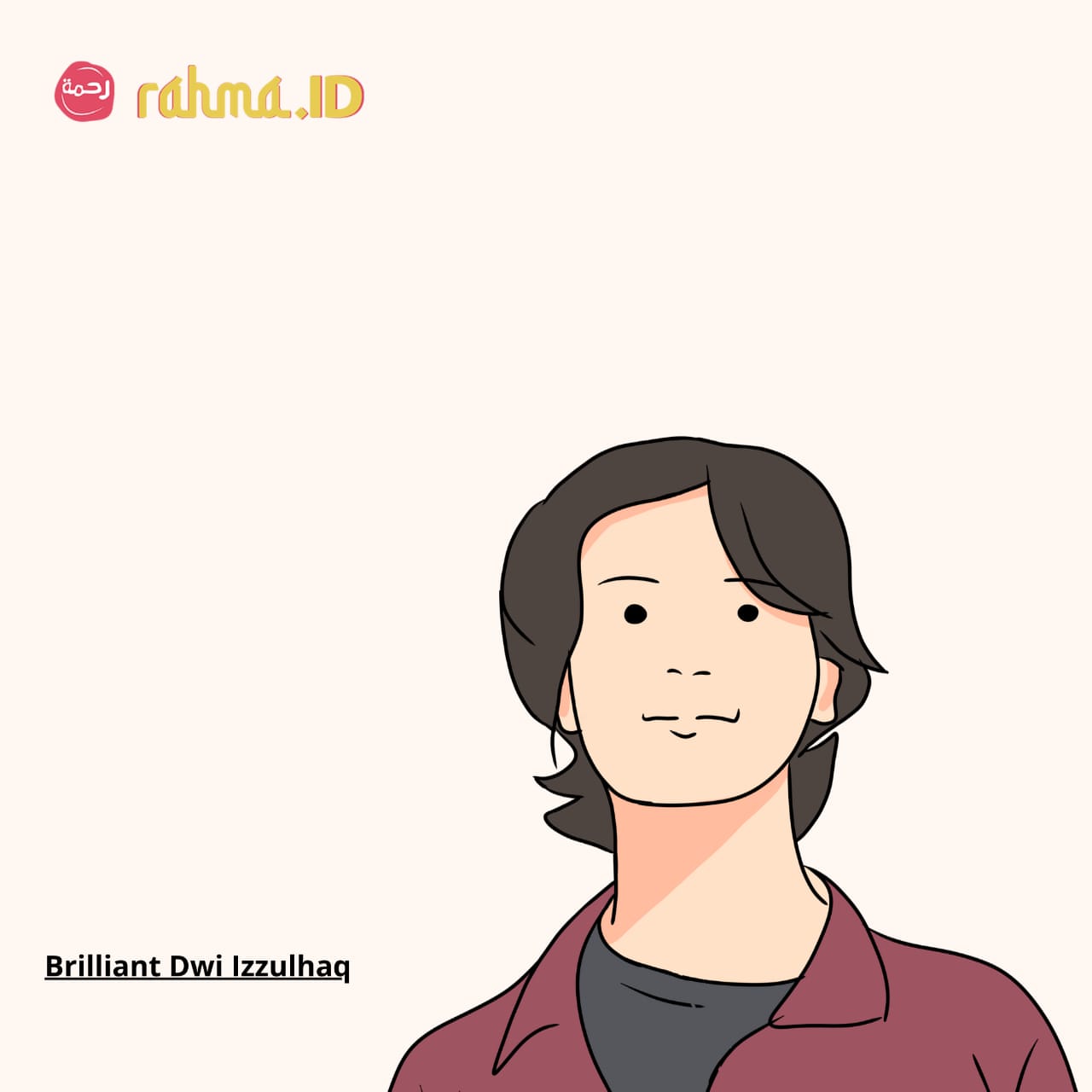
Di Sekolah, Anak Nggak Harus Pintar!
Oleh: Brilliant Dwi Izzulhaq*
Hari itu liga champions tengah berlangsung. Semua mendadak demam sepak bola. Saya, kakak, dan Bapak saya jadi gemar nonton televisi. Bukan untuk sinetron atau kartunnya, tapi untuk laga sepak bolanya.
Kalau sedang hoki, saya dan kakak saya biasanya diperbolehkan Bapak untuk tidur lebih larut supaya bisa menonton pertandingan seru—karena biasanya derbi-derbi memang selalu bertepatan dengan larut malam. Selain karena menyenangkan, sebagai orang yang tinggal di lingkungan yang sepakbola sentris, mengetahui info terbaru seputar sepakbola adalah cara saya bergaul.
Demam liga champions ini juga serius dampaknya. Hampir setiap malam saya jadi ketagihan menonton. Saya sampai hafal dan malah sudah jadi kebiasaan menemani Bapak menonton klub jagoannya bertanding.
Ya, meskipun biasanya lebih sering ketidurannya ketimbang menonton benerannya. Tapi sesedikit-sedikitnya, kami menonton.
Demam Nonton Bola Sekeluarga
Demam liga champions juga ternyata berdampak bukan cuman ke saya, kakak, dan juga Bapak. Tapi juga ke Ibu. Sebenarnya, Ibu memang gak begitu suka menonton pertandingan sepak bola. Saya yakin ia pasti akan lebih memilih menonton sinteron Cinta Fitri ketimbang harus menonton Barcelona melawan Real Madrid.
Tapi apa daya? Kalau anak-anaknya sudah anteng di depan televisi sambil teriak-teriak ‘gol!’, itu artinya Ibu cuma punya satu pilihan: Ikut nonton. Makanya gak heran, semakin sering Ibu ikut nonton, pengetahuannya soal sepakbola juga bertambah. Sesedikit-sedikitnya, Ibu hafal nama pemain top sepakbola.
Teringat Rangking Sepuluh Besar
Bahkan hingga saya sudah menjadi mahasiswa, ingatan Ibu soal sepakbola juga tetap tinggal. Suatu ketika di suatu pagi, saat Bapak dan Ibu sedang asyik ngobrol di teras, saya iseng bertanya ke mereka.
“Pak, Bu, dulu waktu aku masuk peringkat sepuluh besar di sekolah, Bapak dan Ibu bangga gak?” tanya saya.
“Bangga dong, Mas. Tapi, memangnya pernah, ya?” jawab Ibu sambil meledek. Wajahnya sudah gak semuda dulu. Senyumnya kini juga bukan cuma bertabur kebahagiaan, tapi sudah mulai bercampur dengan keriput-keriput kecil.
“Lho, enak saja. Meskipun rapotku banyak jeleknya, tapi sesekali aku pernah lho bu masuk sepuluh besar!” jawab saya singkat membalas bercanda Ibu.
“Oh iya, pernah ya. Maklum, Mas. Namanya manusia. Lebih mudah ingat keburukan daripada kebaikan. Hehehe.” jawab Ibu. Bapak cuma cengar-cengir saja. Ia nampak anteng mendengarkan kami ngobrol sambil membaca koran pagi langganannya.
“Bu, tapi aku serius, lho. Ibu pernah nyeritain aku ke tetangga gak waktu aku masuk sepuluh besar?” tanya saya serius sambil agak tertawa.
“Ya kalau ditanya bangga, ya bangga, Mas. Tapi, Mas Ian baik dulu maupun sekarang juga masih banyak malasnya. Harus ditingkatkan lagi belajar dan ibadahnya. Lagipula buat apa Ibu sampai cerita ke tetangga, Mas? Kamu ini ada-ada saja. Kecuali Ibu menang arisan, baru ibu cerita!” jawab Ibu. Kali ini gantian Ibu yang agak tertawa.
“Memangnya kenapa, Mas? Kok tumben. Tugas?” tanya Bapak, gantian.
“Bukan, Pak. Aku tadi cuma kebetulan kepikiran saja. Aku termasuk beruntung karena meskipun aku gak pernah peringkat satu di sekolah, Bapak dan Ibu gak pernah marah.” Jawab saya singkat.
Mendengar jawaban saya, Bapak dan Ibu tersenyum tipis. Bapak melipat korannya dan kemudian mulai membenarkan posisi duduknya.
Menagapa Marah Saat Anak Tak Dapat Rangking Sepuluh Besar?
“Kenapa harus marah, Mas?” tanya Bapak.
“Ya, kan tiap orangtua mau anaknya jadi cerdas, Pak. Bapak dan Ibu juga pasti begitu.” sambar saya.
“Kalau itu sih benar. Tapi kan cerdas juga bukan segalanya. Sejak kapan peringkat di rapot itu penentu kesuksesan, Mas. Bapak dulu di sekolah pernah punya nilai merah di rapot. Tapi buktinya sekarang tetap bisa kemana-mana dan dibayar, lagi.” jawab Bapak agak nyengir. Dia menatap saya dalam-dalam seraya memasang wajah nggaya.
“Mas, Bapak gak marah kalau Mas Ian dapat nilai jelek. Tapi Bapak pasti marah kalau Mas Ian jadi pemalas. Itu dua hal yang jelas berlainan.” lanjut Bapak.
Saya kemudian terdiam sejenak. Udara pagi itu terasa sangat sejuk. Obrolan kami jadi semakin khidmat.
“Kenapa, Pak?” tanya saya bingung.
“Karena orang yang nilainya jelek itu minimal pernah berjuang. Lain hal dengan orang malas. Mencoba saja belum, tapi sudah berharap hasilnya bagus. Orang yang malas itu akan sulit hidupnya dimasa depan, Mas. Coba kamu perhatikan Jepang.” jawab Bapak.
“Kenapa Pak memangnya?” tanya saya.
Belajar dari Naruto
“Perhatikan itu Sunarto.” jawab Bapak percaya diri.
“Naruto, Pak! Sunarto itu tetangga kita!” jawab saya dengan nada agak kesal. Ibu yang mendengarnya cekikikan.
“Oh iya maaf maksudnya Naruto. Lupa. Tapi coba Mas Ian belajar dari Naruto. Naruto itu kan digambarkan sebagai sosok yang bodoh. Gak punya teman. Tapi ia terus berlatih. Terus berjuang hingga ia kemudian bisa menjadi pemimpin di desanya, Mas. Jadi Naruto itu berhasil bukan karena ia cerdas, Mas. Tapi karena bekerja keras dan tidak malas.” jawab Bapak.
“Iya juga, ya.” Kata saya dalam hati. Mendengar itu saya mendadak tersenyum.
“Pintar dan cerdas itu memang perlu, Mas. Tapi di sekolah, salah kalau kita mengukur kecerdasan dan kepintaran cuman dari selembar kertas berisi nilai. Jadi ya gakpapa Mas Ian nilainya dulu nilainya jelek. Yang penting Mas Ian punya komitmen untuk terus belajar. Kayak Naruto gitu, lah. Naruto kan tontonan dan idola Mas Ian sejak masih SD.” lanjut Bapak.
Omongan Bapak hari itu ibarat sarapan pagi yang amat berat buat saya. Tapi saya tetap bersyukur, meskipun berat. Omongan bapak juga bergizi. Hitung-hitung menambah asupan otak.
“Sudah, Mas Ian beres-beres. Kan hari ini kuliah. Ingat, Mas. Sekolah itu gak harus pintar. Sesekali kita memang perlu mengukur diri dan bersaing. Tapi meskipun begitu, sekolah juga bukan balapan. Jadi, kalau sewaktu-waktu gak melesat cepat jadi nomor satu kayak pembalap Messi juga gak masalah.” sambar Ibu mengingatkan.
Saya kemudian menyerna omongan Ibu sebentar. Terdengar apik tapi kok terasa janggal. Setelah sekian hening, barulah saya tersadar.
“Bu. Messi itu pemain sepakbola. Yang melesat cepat itu bukan pembalap Messi. Tapi Rossi!” jawab saya lantang. Bapak dan Ibu kemudian terbahak-bahak tertawa di depan teras. Sementara saya memutuskan untuk pergi bersiap, Bapak dan Ibu kemudian melanjutkan aktivitas mereka masing-masing dengan senyum yang masih mengembang di wajahnya.
*) Penulis adalah mahasiswa pendidikan di UIN Jakarta dan juga adalah aktivis pendidikan di Tangerang Selatan.
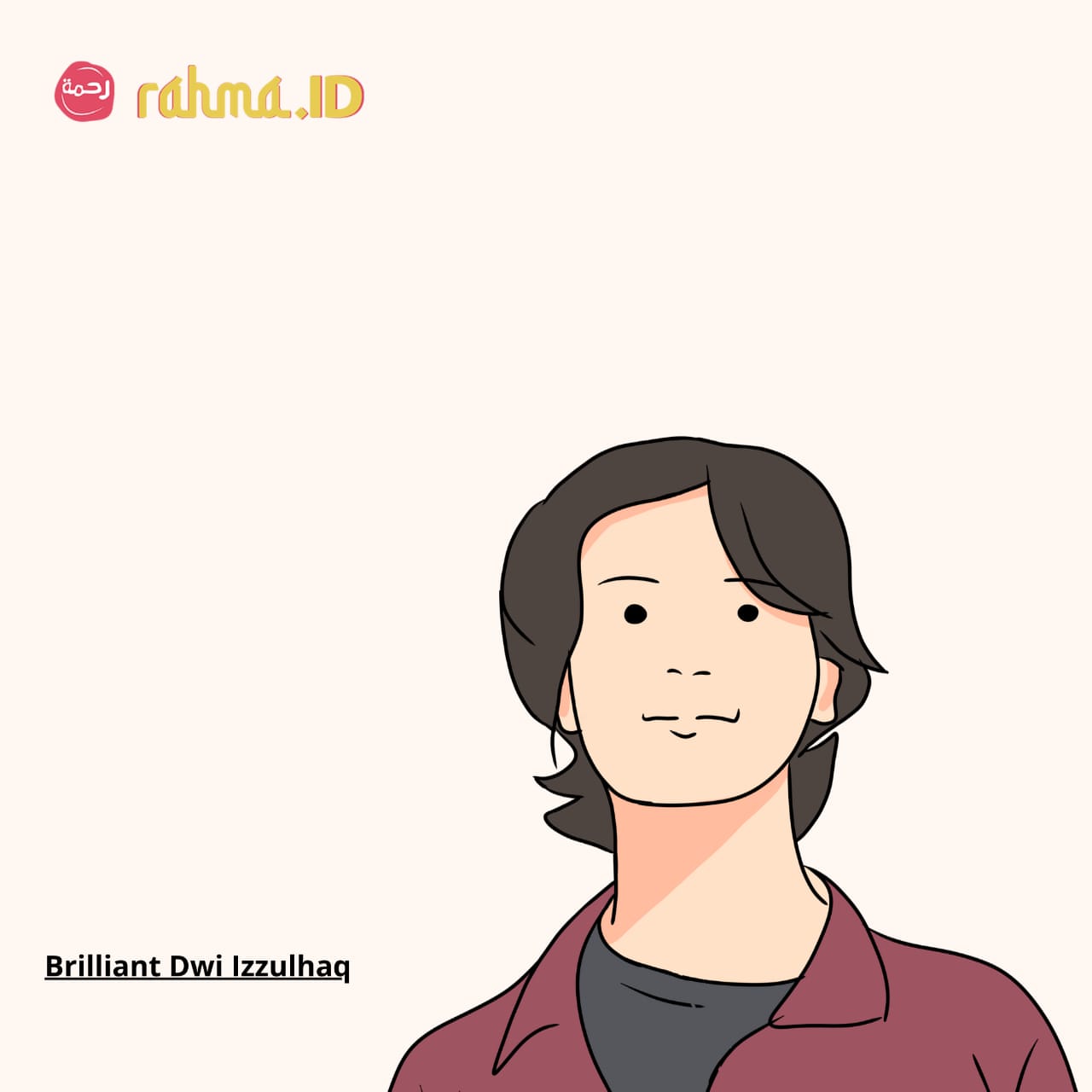
Mahasiswa pendidikan di UIN Jakarta yang kebetulan juga adalah aktivis pendidikan di Tangerang Selatan




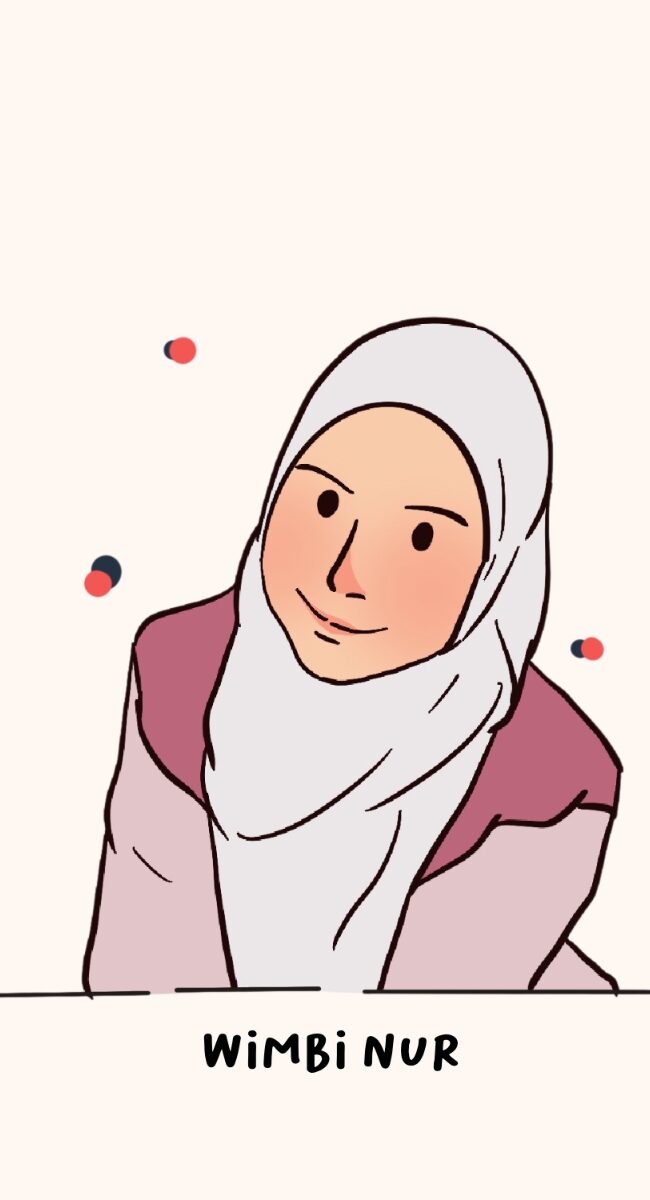

Ndah
Keren banget tulisannya, menginspirasi 👍