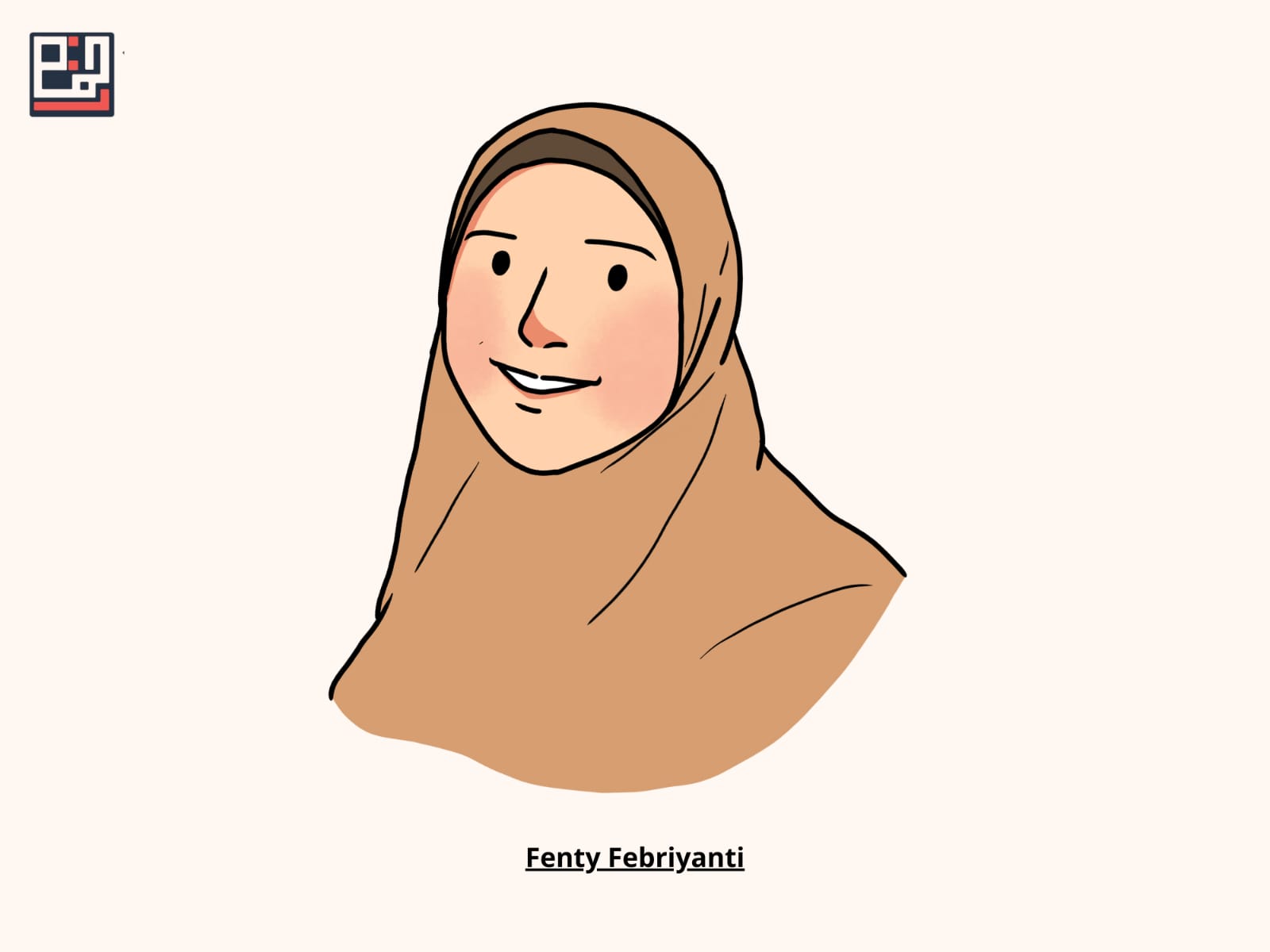
Benturan-Benturan Menuju Dapur yang Lentur (2)
Tapi secara praktik, ia tak pernah belajar memasak. Bahkan saat ia menikah dan pindah ke Cambridge mengikuti suaminya, ia tak bisa memasak apa pun. Saat itu ia berusia 21 tahun dan makanan adalah hal pertama yang membuatnya mengalami kekosongan. Suasana Britania yang dingin—baik dalam arti cuaca maupun karakter orangnya—membuat ia merindukan kampung halamannya. Hingga suatu ketika, saat berjalan-jalan sendirian ia mencium aroma pratha dari sebuah rumah, kerinduannya akan masakan-masakan rumah tak tertahankan lagi. Dengan persetujuan suaminya, ia pulang ke India, belajar memasak dari ibu dan keluarga besarnya.
Setahun kemudian, di Cambridge, tepatnya di dapur rumahnya, Asma mulai memasak. Dengan berbekal referensi makanan yang luas—yang ia dapat dari darah dua klan bangsawan orang tuanya yang juga berasal dari dua daerah yang berbeda, membuat kemampuan memasaknya makin terasah, meski harus ia lakukan di sela kesibukannya menyelesaikan pendidikan Ph.D pada bidang hukum di King’s College.
Dalam kesenyapan, Asma membangun dunianya sendiri. Ia mengundang beberapa pengasuh dan ibu rumah tangga Asia Selatan yang ia temui di sekolah anaknya untuk makan malam. Makan malam yang semula hanya menjadi ajang sosialita itu, pada tahun 2012, mulai berkembang menjadi Klub Makan Malam (Supper Club). Sejak itu pula, selama lima tahun—saat suaminya sedang dinas luar—Asma akan memasak untuk 20, 30, 40 orang yang duduk melingkar di meja besar rumahnya.
Meski Asma menikmati memasak untuk banyak orang di rumahnya, namun tidak dengan kedua anaknya: mereka mulai mengeluhkan hilangnya ruang pribadi mereka. Pun, sang suami, sebenarnya juga tidak terlalu setuju Asma menelantarkan gelar akademiknya hanya demi memasak. Namun, bagi Asma memasak tidak hanya soal mengolah masakan di dapur. Lebih dari itu, memasak membuatnya bahagia.
***
Setelah klub makan malamnya berpindah-pindah tempat, akhirnya pada tahun 2017, Asma membuka Darjeeling Express: sebuah restoran dengan 56 kursi di bilangan Soho. Restoran yang semua pekerjanya adalah perempuan ini, mengusung konsep kekeluargaan sebagai aksen utamanya, tentu selain komponen cita rasa masakan itu sendiri. Asma, akan berkeliling dari satu meja ke meja lain untuk mendongeng soal cerita di balik menu yang terhidang untuk para pelanggan itu. Dan, ya, Darjeeling Express memang bukan sekadar tempat makan, selain menjual kehangatan, ia juga perwujudan dari mimpi-mimpi Asma tentang pemberdayaan perempuan, terutama perempuan Asia Selatan.
Seluruh pekerjanya tidak pernah mengenyam pendidikan memasak. Mereka adalah perempuan pekerja paruh waktu atau ibu rumah tangga yang kemudian menyediakan waktunya penuh untuk bekerja di Darjeeling Express. Mereka adalah pejuang keluarga yang mulai menekuni dunia memasak saat usia tak lagi muda.
Membaca Trisha dan Asma, rasanya ada sedikit bagian diri saya yang serupa. Sampai tahun lalu, ketika usia mencapai 40 tahun, saya menerima keadaan bahwa barangkali memang saya tidak ditakdirkan untuk bisa memasak.
Dengan latar belakang gemar makan, namun tak pernah berkecimpung di dapur, membuat saya buta tentang segala bumbu dan bermacam cara memasak. Ibu saya memang mencintai memasak. Namun Ibu juga menjadikan dapur sebagai area kekuasaannya. Saat di dapur, sesekali Ibu memang meminta bantuan anak-anaknya, namun aturannya jelas: lakukan hanya yang Ibu perintahkan. Bagaimana jika sedikit melenceng? Jangan coba-coba!
Karenanya saya melihat dapur sebagai area yang menegangkan. Semacam pengadilan yang menghasilkan keputusan benar atau salah, dan sialnya saya lebih sering salah ketimbang benar.
***
Barangkali benar, bahwa kita kadang berhutang hal-hal baik pada hal-hal buruk. Pandemi datang tanpa uluk salam. Ia mengikat erat gerak kita seperti karat. Tapi dari situlah muncul siasat-siasat dahsyat untuk melindas kebosanan di rumah. Salah satunya adalah membikin kue. Dan saya memilih hal itu. Tanpa kemampuan apa pun, jelas saya hanya bermodal kenekatan belaka. Namun, siapa sangka brownies perdana bikinan saya justru tandas tak bersisa? Dan, seperti kata Mike Tyson, “Setiap kemenangan, baik atau buruk, memberimu lebih banyak kepercayaan diri,” begitulah yang saya alami. Dada saya terasa penuh dengan luapan kebanggaan.
Sejak itu, semangat saya menderas bak air bah. Saya mulai menguji coba resep-resep kue lain dan mulai merambah resep masakan. Berbeda dengan kebanyakan orang yang merasa terintimidasi dengan resep kue yang tinggi determinasinya, saya justru gentar ketika berurusan dengan memasak. Bagi saya, memasak justru menuntut lebih banyak keberanian untuk bereksplorasi, dan tentu kepekaan cita rasa kita diuji. Bagaimanapun, tak seperti takaran bahan kue yang presisi, banyak bahan-bahan penentu rasa dalam masakan justru ditakar dengan ukuran secukupnya atau sesuai selera. Ada ruang toleransi yang longgar yang menantang kita untuk berekspresi.
Berhadapan dengan pisau bermata dua semacam itu, agaknya tinggal di Indonesia adalah keberuntungan dari langit bagi orang yang tak pintar memasak semacam saya. Melimpahnya berbagai macam rempah, membuat masakan apa pun jadi lebih mudah diterima lidah. Bagaimana tidak? Tinggal cemplang-cemplung kapulaga, cengkih, kembang lawang, dan kayu manis ke dalam kaldu iga, lalu biarkan semua bahan itu menyatu dalam cairan yang dijerang di atas api kecil, jadi sudah sepanci sop yang—bahkan aromanya saja terlampau sulit diabaikan.
Sejak itu, diam-diam, saya merasa bahwa dapur menjadi lebih ramah dan memasak tidak seseram yang saya bayangkan. Bahkan, saya mulai meragukan klaim tak bisa memasak atas diri saya sendiri.
***
Kini di usia 41 tahun, beberapa resep berhasil saya duplikasi dengan sangat baik, separuhnya lagi baik, sisanya lumayan. Hubungan saya dengan dapur makin akrab. Rebusan daging, tumisan bawang, ulekan bumbu, dan letupan minyak yang sedang mematangkan apapun yang berada di atasnya seperti pernak-pernik pembicaraan yang mencairkan suasana.
Tentu kemampuan dan pencapaian saya soal memasak masih sangat jauh jika dibandingkan dengan Trisha dan Asma. Tapi, barangkali kami pernah berada dalam satu kelompok perempuan yang sama. Satu kelompok perempuan yang tidak berkecimpung di dapur sejak dini. Kalaupun dalam budaya terdahulu, masyarakat membuat aturan tak tertulis soal kapan perempuan seharusnya sudah bisa memasak, jelas sudah kami tidak mematuhi tenggat waktu tersebut.
Namun, bagi saya pribadi menyerah pada klaim yang tanpa sadar kerap kita amini sebagai takdir, boleh jadi bukan jalan keluar. Begitu pun terlalu bergegas memburu kepantasan, barangkali juga tak akan menghasilkan apa pun selain kelelahan. Bergerak di antara keduanya mungkin menjadi cara yang paling ampuh untuk menangkap momentum saat ia datang. Momentum bisa datang lebih cepat, bisa juga datang lebih lambat. Kita tak pernah tahu. Maka kemauan untuk terus bergerak menjadi sangat penting.
Dapur dalam pandangan saya kini, adalah sesuatu yang lentur. Kita bisa kembali ke sana kapan saja kita mau, dan saya yakin ia akan tetap menerima. Pasti!
Ibu rumah tangga yang menulis cerpen dan esai, dan sesekali bekerja sebagai editor lepas. Tulisannya pernah dimuat di Buruan.co dengan judul “Secuil Ingatan dan Hal-Hal Kecil di Belakangnya.” Email: fentyfebrianty02@gmail.com
Facebook: Fenty Febriyanti Instagram: febriyantifenty





