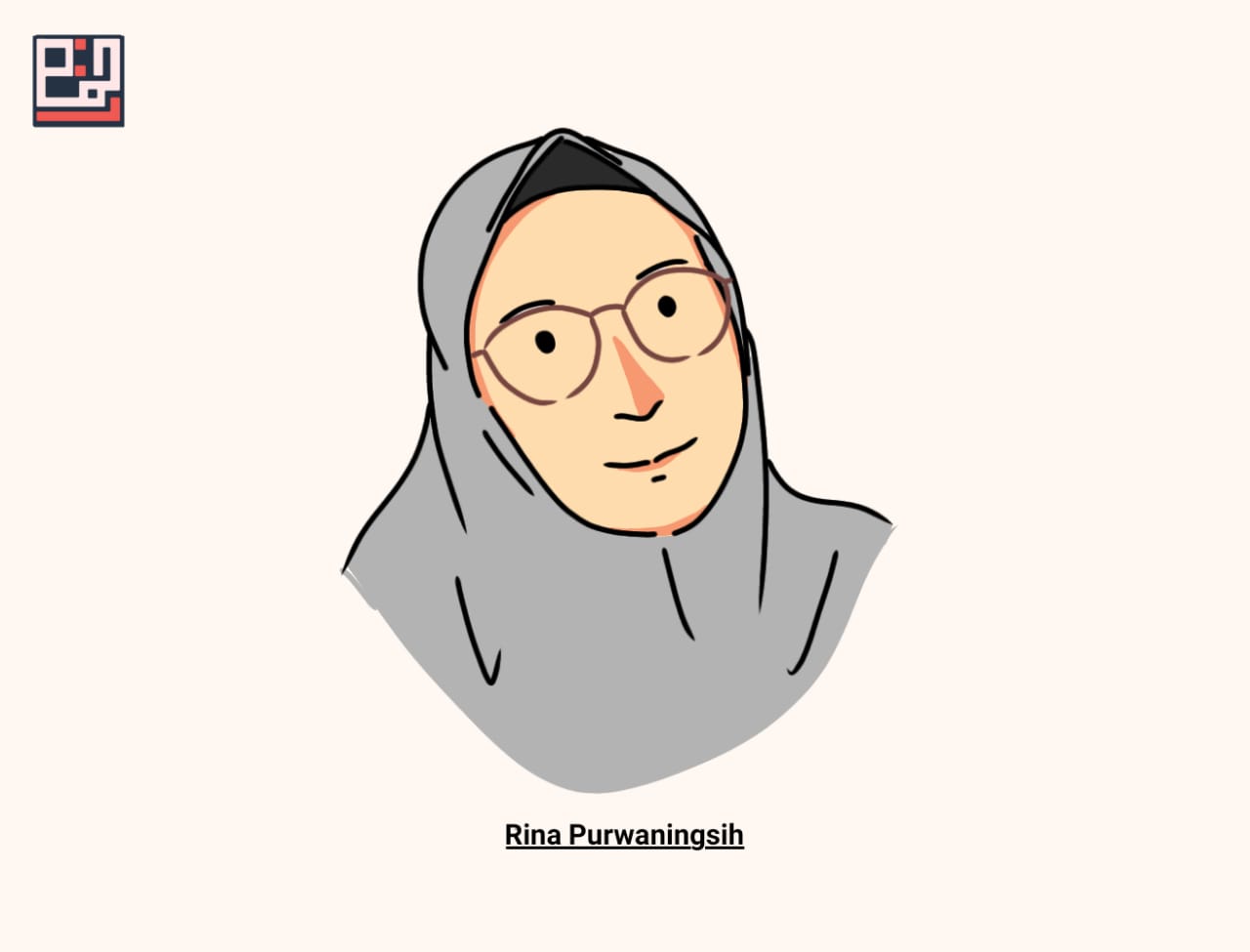
Menyandang Disabilitas Psikososial Bukan Halangan Berkeluarga
Menjadi penyandang disabilitas mental psikososial tidaklah mudah. Di beberapa komunitas disabilitas mental yang saya ikuti, saya sering menemukan curhat beberapa anggota komunitas yang pesimis dengan masa depan mereka, apakah bisa membangun keluarga atau memiliki anak seperti layaknya orang “normal” pada umumnya.
Siapakah penyandang disabilitas psikososial? Menurut UU no. 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, penyandang disabilitas psikososial adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang menimbulkan hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia. Beberapa di antaranya adalah skizofrenia, bipolar, depresi, dan gangguan kepribadian.
Adanya hambatan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari memunculkan rasa pesimis dan ketakutan tentang masa depan. Padahal jika dibiarkan, kondisi seperti itu semakin memperparah kondisi mental mereka. Yang lebih parah lagi jika pesimis itu berubah menjadi rasa putus asa yang bisa menjadi pemicu pikiran untuk bunuh diri (suicidal thought).
Berkaca dari fenomena itu, saya teringat dengan tiga kawan saya. Pertama adalah Dewi, seorang penyintas bipolar, yang kedua adalah Hana, juga penyintas bipolar dan yang ketiga adalah Kusuma, penyintas skizofrenia. Ketiganya menikah, memiliki anak dan menjalani kehidupan seperti orang kebanyakan. Ketiga kawan saya itu menunjukkan bahwa menjadi penyintas gangguan mental bukan akhir dari segalanya.
Apa Pemicunya?
Latar belakang pemicu disabilitas pikososial baik bipolar maupun skizofrenia bersifat sangat kompleks. Saya memperoleh dua sumber yang berbeda untuk dua jenis gangguan tersebut. Pertama adalah dokter Jiemi Ardian Sp.KJ, menjelasakan tentang penyebab bipolar dalam channel Youtube Greatmind. Sedangkan dokter Dharmady Agus, SpKJ memberikan penjelasan tentang skizofrenia melalui youtube milik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Atmajaya.
Baik Jiemi maupun Dharmady, keduanya sepakat bahwa penyebab bipolar dan skizofrenia bersifat multifaktorial-banyak faktor. Penyebabnya bisa faktor genetik, komplikasi saat kehamilan dan persalinan, kondisi neurochemichal pada otak yang tidak seimbang, faktor stress atau psikososial, dan pola asuh yang salah.
Dewi, Hana, dan Kusuma sama-sama memiliki masa kecil yang suram, terkait dengan pola asuh kedua orang tuanya. Hana mengalami kekerasan berulang yang membuatnya mengalami trauma berkepanjangan. Sedangkan Kusuma, adanya komplikasi kehamilan, kelahiran dan baby blues yang tak tertangani lantas memicu gejala skizofrenia.
Begitu kompleksnya penyebab kedua disabilitas tersebut, maka penanganannya pun tidak sederhana. Ada psikoterapi, terapi obat, dukungan lingkungan, dan orang-orang terdekat. Dari kondisi tersebut, bisakah seorang penyintas bipolar dan skizofrenia berkeluarga? Mengingat membangun rumah tangga berarti seseorang mengemban tanggung jawab besar yang tidak mudah.
Bisa!
Mengapa saya yakin dengan jawaban itu? Karena pada dasarnya seorang individu tetap menjadi dirinya sendiri. Menjadi penyintas skizofrenia, bipolar dan gangguan mental lainnya tidak lantas mengubah seseorang menjadi orang lain. Penyintas tetap menjadi manusia utuh yang memiliki kehendak, prinsip dan tujuan hidup. Yang menjadi pembeda hanyalah sakit psikis yang mereka alami.
Contohnya adalah pendapat dari pasangan Dewi dan Kusuma. Mereka menemukan istrinya menderita penyakit psikis pasca pernikahan. Sebelum menikah mereka telah saling mengenal satu sama lain, merasa satu visi dan kemudian memutuskan untuk hidup bersama. Apa yang terjadi pada istri mereka tidak begitu saja mengubah pandangan mereka. Istri mereka adalah orang yang sama saat awal mereka kenal.
Baik Kusuma maupun Dewi termasuk beruntung. Mereka memiliki support system yang positif. Suami dan keluarga suami bahu-membahu membantu menjalankan roda rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak dan hal lain yang tidak bisa penyintas lakukan. Suami mereka sebagai caregiver memegang prinsip untuk mempertahankan pernikahan, yang terefleksi pada sikap tanggung-jawab dan kepedulian.
Sebaliknya, Dewi berusaha mengatasi keadaannya. Mengenali kebutuhan diri, meminimalisir pemicu, dan memberi batasan atas hal berada yang di luar kendalinya. Sedangkan Kusuma, menyadari dirinya sebagai orang yang keras dan mudah marah. Dia terus berlatih mengendalikan emosi dengan mindfulness yang dia pelajari sendiri. Saat dia lebih tenang, mampu mengatasi dirinya sendiri, suami dan anak pun mengikuti.
Hana, tidak seberuntung Dewi dan Kusuma. Dia tidak memiliki support system yang baik. Pada awalnya percekcokan lebih sering terjadi. Suaminya hanya tahu istrinya memiliki trauma namun tidak mengerti tentang adanya penyakit psikis. Ia berpikir, emosi istrinya yang meledak-ledak disebabkan karakter yang sensitif tapi dia tetap yakin pada dasarnya istrinya memiliki karakter yang baik.
Tak mendapatkan dukungan siapapun tidak menyebabkan Hana patah arang. Langkah awal yang dia lakukan adalah keluar dari lingkungan pekerjaan toksik yang memperparah depresinya. Dia mencari pertolongan psikiater, mencari informasi dari buku atau medsos tentang self–improvement dan mindfullness, serta mencari kesibukan sebagai pengalihan fokus.
Dalam proses pencarian, akhirnya Hana menemukan komunitas yang mendukung, dan menerima dia apa adanya. Melihat perjuangan istrinya, lambat laun, suami Hana terbuka dan memahami bahwa gangguan psikis berpengaruh kepada naik turunnya sikap dan kesehatan fisik istrinya. Dia mendukung pengobatan dan berusaha menghindari segala sesuatu yang men-trigger fase depresi istrinya.
Ada kesamaan di antara ketiga pasangan sebagai penyintas disabilitas psikososial tersebut dalam menjalani pernikahan. Mereka memilki tujuan pernikahan yang kuat, saling mengenal dengan baik karakter pasangan, saling menyadari hal-hal pemicu untuk mencegah relaps (kekambuhan), juga treatment supaya penyintas bisa berdaya menjalani kesehariannya.
Kesadaran yang terbentuk juga harus dibarengi dengan kesabaran. Pernikahan, baik “umum” maupun dengan penyintas pada dasarnya sama. Tak ada lagi “aku” tapi kita. Sabar menghadapi, sabar untuk bersedia berubah demi kebaikan bersama. Sabar tidak terwujud sendiri tanpa adanya keihklasan. Ikhlas menerima bahwa ini semua adalah kehendak Allah semata. Manusia hanya berkewajiban menjalaninya.
Sikap tidak mempermasalahkan masalah juga perlu menjadi sebuah kesadaran. Karena hidup itu sendiri hakikatnya adalah masalah. Masalah adalah tugas hidup yang harus diselesaikan, bukan untuk memisahkan dan bukan tanda berakhirnya sesuatu. Sadar, ikhlas dan sabar. Itu saja!
Penulis: Rina Purwaningsih Editor: Isnatul Chasanah
Guru yang masih terus berguru





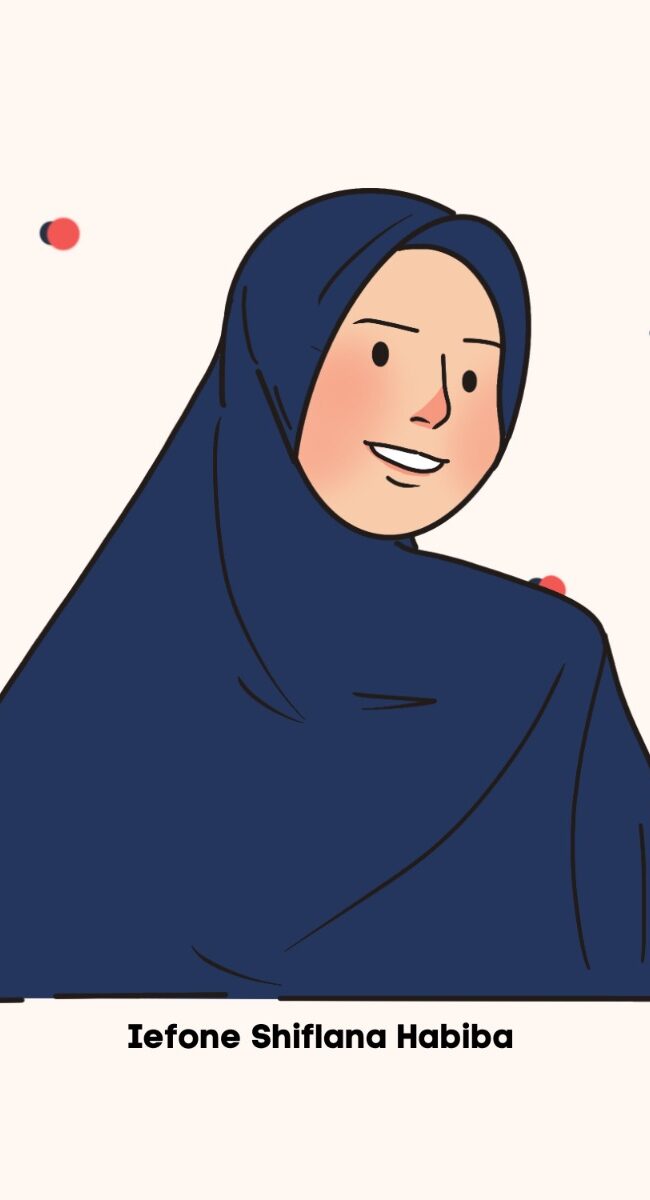
Dea
Saya di jogja, mau sekali untuk bergabung dgan komunitas2 kesehatan mental, yg bisa kumpul2 dan ngobrol2, tpi blum berhasil dapat. Selama ini disimpen sndiri aj, pdhal klo ketemu temen2 yg sepaham bisa lebih ringan bebannya. Ada saran?
Terimakasih