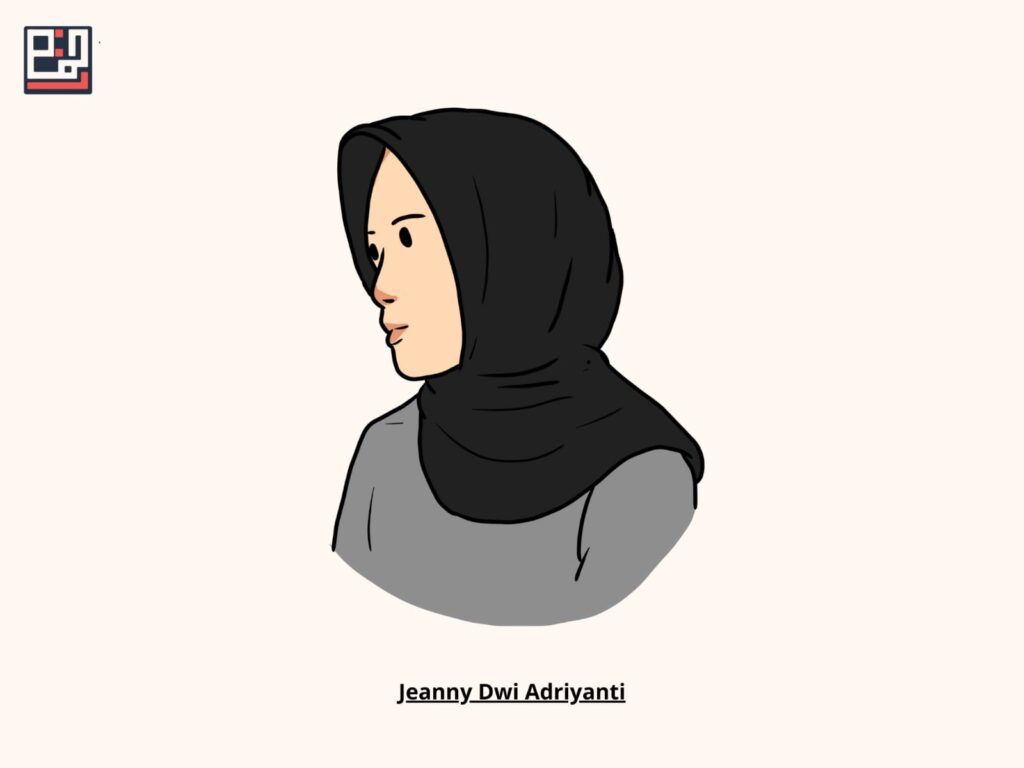Perempuan kini mendapat kepercayaan yang lebih baik sebagai agen resolusi komflik. Komitmen Indonesia untuk melibatkan perempuan dalam proses penyelesaian konflik masih perlu mendapat penguatan. Pada bulan November 2020, Menteri Perbedaayaan Perempuan Indonesia melalui RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial), membuat Indonesia tercatat sumbangsihnya sebagai agen penjaga perdamaian perempuan terbesar ke-7 di dunia dan pertama di Asia Tenggara.
Namun keadilan di antara sesama perempuan harus menjadi perhatian. Prinsip egaliter gender antara kaum perempuan dan laki-laki kini sudah tidak menjadi permasalahan utama. Sudah sangat banyak contoh mereka-mereka yang mampu menduduki posisi hingga menjalankan peran yang sebelumnya hanya dilakukan oleh laki-laki. Sosok Nyai Sholichah yang merupakan cucu pendiri NU (Nahdlatul Ulama) dan berprofesi sebagai dokter spesialis paru. Beliau pernah menjadi agen resolusi konflik saat terjadi konflik di antara pembesar NU. Kala itu tidak umum bagi wanita untuk maju menjadi agen perdamaian, yang umum adalah berada di balik layar, di belakang para pembesar, menyiapkan segala kebutuhan rapat.
Pendidikan sudah semestinya tidak hanya membagikan warisan-warisan ilmu santifik namun juga dengan kemampuan analisa permasalahan sosial. Literasi mengenai resolusi konflik masih minim khususnya pada kaum perempuan. Persyarikatan Muhammadiyah melalui Aisyiyah menjadi simbol integritas dan intelektualitas kaum perempuan dengan berbagai gerakannya berperan besar dalam membentuk karakter perempuan sebagai agen perdamaian. Melawan hegemoni tradisi Indonesia.
***
Menyoroti hal yang sering luput, yaitu semakin kompetitif peran perempuan, maka keadilan antar sesama perempuan harus kita perjuangkan untuk menghindari situasi saling sikut. Apakah sama hak yang diterima oleh mereka kaum perempuan yang lahir di keluarga bangsawan atau konglomerat dengan mereka yang lahir di area pinggiran dengan kondisi status ekonomi menengah ke bawah?
Dalam buku novel “Entrok” karangan Okky Madasari, ada secuil kisah tentang perbedaan antara perempuan Keraton dan perempuan dari kalangan rakyat biasa di Jawa Tengah. Yang bahkan awal mula kebiasaan memakai bra hanya untuk kalangan kerajaan atau keturunan bangsawan. Hingga muncul sosok Marni yang berani muncul menyuarakan hak memakai bra untuk semua perempuan. Semua perempuan berhak menggunakan bra, tidak pandang apakah mereka keturunan nigrat atau rakyat biasa.
Ada benarnya kisah dalam novel tersebut, berdasarkan oleh kedudukan, ilmu serta harta. Karena untuk dapat menggunakan bra saja pasti membutuhkan uang untuk membelinya. Dan bagi rakyat biasa akan lebih memilih menghemat. Selain itu informasi penggunaan bra juga pastinya masih terbatas di kalangan kerajaan. Ini baru tentang pakaian dalam wanita, belum lagi ketika membahas hak dan kemampuan meraih pendidikan yang setara, kompetensi berorganisasi, hingga kemungkinan untuk bisa menjadi jajaran pimpinan sebuah perusahaan.
***
Yang menjadi pokok bahasan bukanlah semata-mata mengenai penggunaan bra, ia hanyalah sepenggal kisah simbol ketidakseimbangan hak sesama kaum perempuan. Sangat miris, ketika menyebutkan perbedaan perempuan Keraton dan perempuan dari kalangan rakyat biasa yang rasa-rasanya memiliki nilai yang jauh berbeda, padahal mereka adalah sesama perempuan. Satu gender, namun berbeda posisi. Yang satu mendapat anugerah harta, tahta, dan pujaan. Yang satu mendapat anugerah kekuatan, keberanian dan realita.
Tidak sedikit yang menganggap kasta hanya berdasarkan gelar kedaerahan, ataupun kedudukan. Status pendidikan tinggi pun ternyata tidak menjamin seorang perempuan akan dihargai oleh lingkungannya. Stigma sosial yang negatif dari masyarakat akan mudah melekat pada perempuan yang tidak memenuhi standar sosial masyarakat. Standar tersebut meliputi batasan usia menikah, batasan usia memiliki anak, batasan penghasilan untuk dibandingkan dengan penghasilan suami, serta batasan jenis pekerjaan sesuai pandangan norma masing-masing.
Tidak sedikit perempuan dari kalangan rakyat biasa yang selalu mengidam-idamkan menjadi putri istana. Terlalu banyak kisah fiksi dalam film yang mengisahkan keburentungan jika menikahi lelaki terhormat nan kaya atau ternyata merupakan putri yang terbuang, yang menumpulkan logika berpikir perempuan. Berangan-angan namun tersentak bila berhadapan dengan realita. Jika tak memandang kedudukan, apakah setiap perempuan memiliki kuasa atas diri mereka untuk menyuarakan hak, berpendapat dan menentukan keputusannya sendiri.
***
Keterlibatan perempuan dalam agen perdamaian dan keamanan harus semakin mendapat perhatian, dengan mengubah stigma bahwa perempuan adalah korban dalam konflik dan mengoptimalkan keadilan sesama perempuan tak pandang kasta dan kedudukan. Keadilan meliputi hak pendidikan yang sama. Dalam menjadi agen resolusi konflik tidak hanya pendidikan yang dibutuhkan, namun juga pola pikir, lingkungan yang suportif, serta otoritas.
Sehingga setiap kesempatan yang bernilai juga harus sama rata. Tidak bisa kita pungkiri banyaknya perlakuan buruk terhadap kaum perempuan, menjadikan perempuan sebagai korban dari konflik. Masih sedikit yang maju untuk dapat menjadi agen resolusi konflik meski dari segi populasi, perempuan kini sudah bukan minoritas lagi.
Tentunya upaya-upaya untuk mendorong perempuan lebih aktif dalam resolusi konflik, menjadi agen perdamaian harus lebih kuat. Tidak hanya menguatkan prinsip egaliter antara kaum laki-laki dan perempuan. Namun yang juga penting ialah mengeliminasi ketidakadilan dan diskriminasi sesama perempuan. Tidak elok menargetkan peran agen perdamaian, sedangkan kebobrokan keadilan di dalamnya masih porak-poranda. Jangan sampai hanya demi entitas sebagai agen perdamaian dunia, namun meninggalkan substansi keadilan yang sebenarnya.