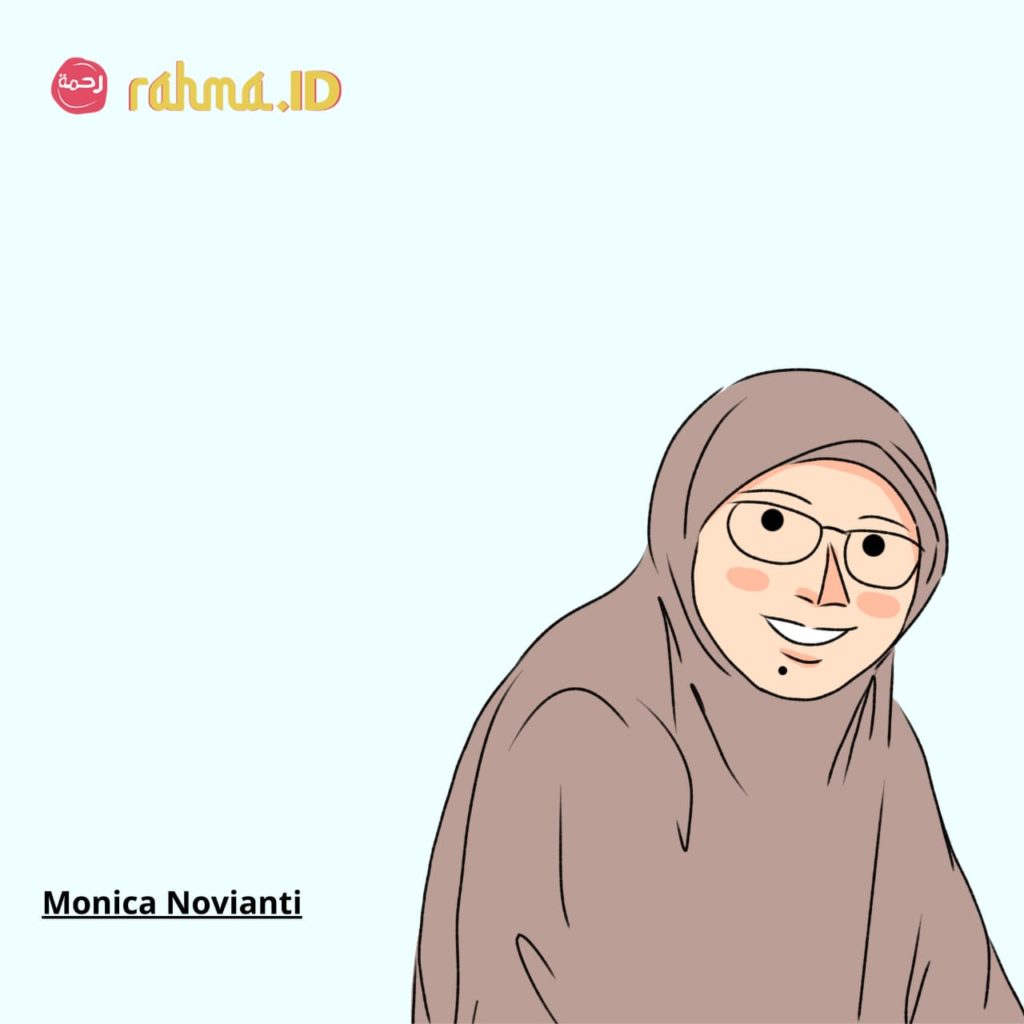Oleh : Monica Novianti*
Sekitar dua tahun silam, ayah saya meninggal dunia. Sebuah kehilangan yang berat tentunya. Namun saya memperoleh pelajaran yang begitu berharga. Sebuah pelajaran yang membuat saya memahami sisi lain diri saya.
Beliau meninggal karena kecelakaan. Motor yang dikendarainya ditabrak oleh seorang remaja yang masih di bawah umur. Tidak lama setelah sampai di rumah sakit, ayah berada dalam kondisi tidak sadar. Saya hanya bisa menatapnya sedih sembari mengharap kalau-kalau beliau akan pulih.
Tetapi ternyata ayah harus dirujuk ke rumah sakit lain yang dinilai mempunyai peralatan yang lebih memadai. Sesampainya di sana, para dokter langsung memeriksanya. Salah satu dokter menyampaikan hasil diagnosanya kepada kami. Ia mengatakan bahwa kondisi ayah sudah sangat buruk. Pendarahan di kepala akibat benturan yang terlalu keras sudah terlampau parah. Mesin ventilatorlah yang membuat detak jantung ayah masih berdegup sehingga secara medis beliau dinyatakan masih hidup.
Saya, ibu, dan kakak tentu saja menjadi cemas. Mau tidak mau kami harus segera mengambil tindakan. Rumah sakit sudah menyerah karena memang keadaan ayah sudah tidak dimungkinkan untuk sembuh. Seumur hidupnya, ia akan terus dalam keadaan tidak sadar serta bergantung pada mesin ventilator.
Kami pun bermusyawarah. Sempat terjadi diskusi yang cukup pelik. Ibu saya jelas tidak menghendaki ayah meninggal. Pun dengan kakak dan diri saya. Tetapi pada saat yang sama, kami pun menyadari bahwa membiarkan ayah seperti itu justru akan semakin membuatnya menderita. Satu-satunya pilihan yang masuk akal ialah membiarkannya pergi.
Segera kami sampaikan ke rumah sakit bahwa kami memilih untuk merelakan ayah. Selanjutnya, rumah sakit memberikan sebuah surat persetujuan yang isinya menyatakan bahwa kami dari pihak keluarga menyetujui tindakan rumah sakit untuk melepas mesin ventilator dari tubuh ayah. Surat tersebut harus ditandatangani oleh salah satu orang dari pihak keluarga.
Kami kembali berada dalam posisi sulit. Tiada satu pun dari kami yang ingin menandatangani surat tersebut. Tentu saja ada perasaan bahwa sama saja kami telah membunuh ayah apabila kami sampai memberikan tanda tangan. Namun jika tidak ada tangan di sana, selamanya ia akan dalam kondisi yang menyedihkan.
Lalu tiba-tiba saya memutuskan bahwa sayalah yang akan menandatanganinya. Sebuah keputusan yang gila barangkali. Bagaimana mungkin saya tega membiarkan ayah saya meninggal? Tetapi jika tidak ada yang bersedia, saya merasa bahwa suka tidak suka saya harus melakukannya.
Hanya butuh waktu beberapa detik untuk membubuhkan tanda tangan ke surat tersebut. Tanpa ragu dan air mata. Segera setelah itu, rumah sakit mencabut mesin ventilator dan menyatakan ayah telah meninggal dunia.
Sampai sekarang, saya masih bertanya-tanya apa yang mendorong saya untuk menandatangani surat tersebut. Bisa jadi sebagian orang menganggap saya manusia berdarah dingin. Di sisi lain, jauh dalam lubuk hati terdalam, saya menginginkan ayah pulih waktu itu. Namun pilihan apa lagi yang saya miliki selain merelakannya pergi untuk selamanya?
Barangkali jawaban yang mampu saya berikan ialah karena saya menginginkan baik keluarga maupun ayah sama-sama tidak menderita. Paparan dari rumah sakit jelas menyebutkan bahwa sangat kecil kemungkinan ayah akan tersadar. Jika kami memaksakan ayah terus dalam kondisi hidup, beliau akan terus terbaring koma dengan mesin ventilator berada di sisinya. Lalu dalam jangka waktu yang tidak tentu, keluarga kami pun juga harus menyaksikan ayah meninggal secara perlahan dan pastinya menyakitkan untuk dilihat. Hal yang saya ketahui saat itu ialah, kehidupan kami semua harus terus berlanjut. Saya, ibu, kakak, dan anggota keluarga yang lain perlu menapak tangga kehidupan kami selanjutnya dengan lebih lapang. Sedangkan bagi ayah, akan lebih baik baginya jika beliau melanjutkan hidup di alam selanjutnya, tanpa ada kesakitan yang dialaminya.
Peristiwa ini pada akhirnya membuat saya belajar untuk tegar manakala harus menjalani pilihan yang tidak mudah. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa tidak selamanya perempuan didominasi oleh emosi ketika mengambil keputusan. Tidak jarang para perempuan harus membiarkan sisi rasionalnya mengambil alih demi kebaikan bersama.
Pelajaran ini juga yang menghindarkan saya untuk meluapkan emosi kepada remaja yang menabrak ayah saya. Sisi rasional saya mengatakan bahwa ia sama sekali tidak bermaksud untuk membunuh ayah. Ia memang lalai dan mengakuinya. Sisi rasional pula yang menahan saya untuk tidak memaki kedua orang tuanya. Mereka memang salah. Namun di saat yang sama saya mengetahui mereka tidak pernah menghendaki tragedi ini terjadi. Saya menyerahkan semua kepada kepolisian untuk menindak remaja tersebut sesuai hukum yang berlaku. Intinya, saya memaafkan mereka.
Karena saya tahu, dengan memaafkan tanpa memaki, kami semua bisa melanjutkan hari-hari ke depan dengan lebih bebas. Sisi rasional kembali menyelamatkan saya untuk terbebas dari beban sebuah kesedihan. Tidak hanya terkait dengan peristwa meninggalnya ayah, pengalaman menandatangani surat “kematian” tersebut membuat saya lebih kuat untuk mengarungi tantangan kehidupan setelahnya hingga kini.
*) Penulis adalah seorang perempuan yang hobi membaca, menulis, menonton film, dan jalan-jalan. Kini menetap di Brisbane, Australia.
Monica Novianti. Penulis kini tinggal di Brisbane, Australia. Hobi membaca, menulis dan jalan-jalan. Kontak: noviantimonica4@gmail.com