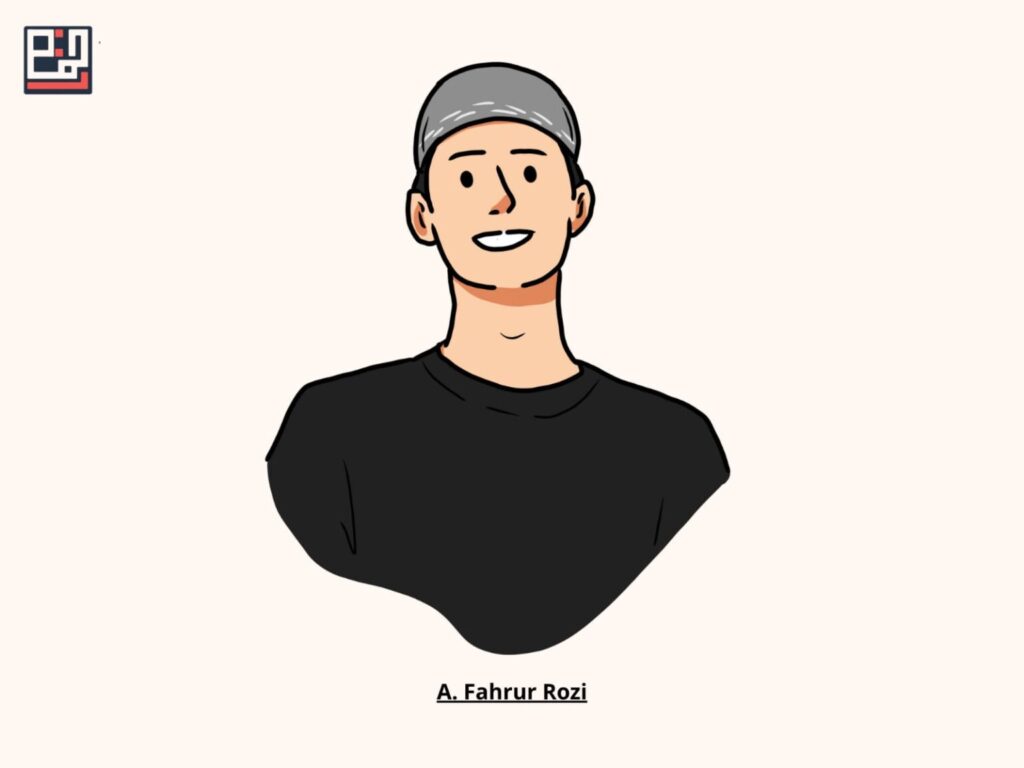Diskursus mengenai agama di era digital dewasa ini kian kompleks. Hal ini sejalan dengan adanya pergeseran nilai-nilai prinsipil secara masif dari waktu ke waktu. Agama yang pada hakikatnya bersifat dinamis dan purifikatif, kian bertransformasi menjadi ekstrimis dan koersif. Ia bukan lagi menjadi wahyu Tuhan, melainkan doktrin paham.
Nalar dan gerakan beragama kian mengalami degradasi nilai dan dekadensi moral. Nalar ekstremisme, gerakan propaganda, dan ujaran kebencian melalui sistem jaringan terbuka seperti media kerap melekat pada tubuh agama. Ia dengan dogma religiositasnya cukup ampuh dalam melegitimasi berbagai kepentingan, seperti politik, ideologi, atau bahkan ekonomi. Implikasi yang terjadi ialah maraknya isu Islamofobia di negara-negara sekuler, tak terkecuali Indonesia.
Melihat situasi terkini, rasanya kita memerlukan sebuah gerakan dakwah berbasis digital dengan mujahid digital sebagai motor penggeraknya. Adalah keniscayaan manakala melihat potensi dan peran yang cukup besar darii para pemuda khususnya sebagai penggerak dakwah di ruang maya.
Kemampuan intelektual dan kompetensi digital pemuda saat ini menempatkan mereka sebagai posisi sentral dalam halakah dakwah Islam. Mujahid digital harus mampu merestorasi, merestrukturisasi, dan merefungsionalisasi konstruksi dakwah yang moderat dalam aksebilitas jaringan secara proporsional.
Upaya tersebut merupakan bentuk ikhtiar dalam mengampanyekan Islam yang moderat (wasathiyah) di ruang-ruang digital. Hal ini mengingat bahwa Islam moderat di Indonesia akhir-akhir ini kian termarjinalkan.
Peran Sentral Mujahid Digital
Halakah digital tentu menjadi oase penyejuk di tengah perseteruan antarpaham. Selain itu, isu propaganda, hoaks, fitnah, bullying, dan narasi adu domba juga kian mewarnai kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia belakangan ini.
Microsoft dalam sebuah survei terbarunya, Digital Civility Index (DCI) menunjukkan bahwa kesantunan masyarakat Indonesia dalam bermedsos cenderung menurun. Survei yang dilakukan selama pandemi pada 2020 dengan mengambil sampel sebanyak 11.067, yang 82%-nya menyatakan bahwa tingkat kesopanan netizen kian memburuk.
Berdasarkan realitas di atas, mujahid digital sebagai penggerak halakah dakwah digital sudah seyogianya dapat berperan dengan menyajikan konten-konten digital berbasis dakwah yang unik nan menarik dengan tetap mempertahankan nilai dan prinsip pluralisme dan multikulturalisme.
Islam sebagai sebuah agama yang dinamis juga perlu mengasosiasikan kearifan lokal dan keluhuran prinsip budaya tradisional di masa lampau dengan visi peradaban digital di era sekarang melalui metode dakwah yang memanfaatkan sarana media digital.
Oleh karenanya, dakwah digital di era kekinian adalah bentuk praksis dari ‘al-muhafadhatu ‘ala qadimi as-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah’, yakni dengan ‘memelihara (budaya) yang lama yang baik dan mengambil (budaya) yang baru yang lebih baik’.
Berdakwah di ruang digital adalah suatu ijtihad eksidensial (‘aridhi). Ia adalah bentuk dorongan moral (imperative of morality) sebab berkembangnya media informasi. Dengan demikian, mujahid digital saat ini juga harus mengarahkan agar dakwah Islam dapat memenuhi ruang-ruang digital.
Fikih Beragama sebagai Landasan Terwujudnya Moderasi Beragama
Seiring perjalanannya, para mujahid digital juga kerap menemukan tantangan yang cukup besar dalam memainkan perannya sebagai penggerak dakwah digital.
Pertama, tantangan untuk segera merumuskan konsep moderasi agama berbasis kesetaraan (equality) sebagai tuntunan fikih beragama yang nondiskriminatif. Rumusan itu hendaknya memuat konsep kesetaraan, hubungan mayoritas-minoritas, terminologi jihad, teologi inklusif, interaksi paham dalam konteks keindonesiaan yang heterogen, dan yang paling penting ialah objektivitas dakwah.
Kalau kita cermati, dalam birokrasi pemerintah sekalipun masih terdapat konsep moderasi beragama yang diskriminatif. Misalnya, pada Peraturan Presiden (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pada peraturan ini nyatanya terdapat penyempitan makna terhadap agama. Pemaknaan terhadap agama hanya terbatas pada agama ‘yang enam’ saja. Akibatnya, dikotomi mayoritas-minoritas semakin tak terelakkan.
Oleh karena berangkat dari perspektif yang dominan, menganggap segala obyek di luar agama tersebut, kendati memiliki sesembahan Yang Maha Esa, eyang guru, ajaran, ritual, aliran kepercayaan, dan tempat peribadatan hanyalah sebatas produk kebudayaan.
Seperti halnya Komunitas Penghayat Spiritual yang mendapat perlakuan alienasi dan berujung pada penggabungan rumpun bersama unit Eselon I Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru hanya karena komunitas tersebut tidak merepresentasikan ajaran agama ‘yang enam’.
Di sini kita melihat bagaimana transformasi diskriminatif konsep moderasi agama; dari diskriminasi normatif, menjadi diskriminasi paradigmatik, hingga menjadi wajah semu budaya kolektif. Imbasnya, obyek pengarusutamaan moderasi beragama selama ini menjadi sempit dan terbatas dalam kungkungan norma perundang-undangan.
Menanggapi hal tersebut, perlu adanya sebuah rumusan ‘Fikih Beragama’ sebagai pijakan sistemik dalam haluan dakwah digital. Fikih itu sendiri bersifat fleksibel dalam menjawab persoalan kontemporer melalui ijtihad (istinbath al-ahkam) para fuqaha.
Adapun rumusan fikih beragama menurut Jasser Auda setidaknya harus memuat enam pilar, di antaranya adalah nalar (al-idrakiyyah), universalitas (al-kulliyat), keterbukaan (al-infitahiyyah), keterpautan satu dengan lainnya (al-harakiriyyah al-mutamadah tabadduliyyan), serta multidimensi dan multiperspektif (ta’addud al-ab’ad) (Asep Salahudin, 2022; 08). Rumusan fikih beragama hendaknya juga harus berorientasi pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan.
Pemujaan Digital
Tantangan selanjutnya adalah wajah ‘digital ghost’ yang menawarkan penghambaan pada akumulasi jumlah monetisasi media. Damhuri Muhammad (2022) dalam “Berani Mati Demi Konten YouTube”, menguraikan aneka fakta tragis kematian yang merenggut nyawa seseorang akibat suatu ‘pemujaan konten’. Orientasi materialistik melalui penghambaan terhadap konten-konten cenderung mendorong seseorang apatis terhadap esensi bermedia.
Misalnya, di Nasvhille, AS Desember 2021, Timothy Wilks (20) meregang nyawa akibat konten prank perampokan yang dia buat sendiri. Selain itu, di Halstad, AS Juni 2017, Pedro Ruiz (28) mati akibat konten prank penembakan terhadap dirinya, atau seorang Youtuber asal Rusia, Stanislav Reshetnikov (30) membuat konten dengan menyiksa kekasihnya yang sedang hamil hingga tewas di tempat. Aksi maut itu nekat dilakukan semata-mata untuk mengejar monetisasi jumlah pemirsa (viewers).
Esensi Bermedia Sosial
Esensi bermedia sudah mengalami degradasi etika dari waktu ke waktu. Para aktivis media saat ini cenderung mencari sensasional dari pada berbagi pengetahuan. Youtuber, misalnya, akhir-akhir ini lebih tertarik membuat konten prank atau aksi ekstrem seperti menghadang truk, tantangan makan kripik mahapedas, atau bercengkrama dengan hewan predator. Itu semua pada kenyataannya lebih memukau dan sensasional ketimbang konten-konten dakwah dan edukasi. Ini yang penulis maksud dengan istilah ‘pemujaan digital’ di mana untuk mencegahnya diperlukan konstruksi kesadaran esensi dan etika bermedia.
Pergeseran nilai bermedsos itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi mujahid digital. Konten-konten keagamaan dakwah digital tentu harus lebih mainstream keberadaannya. Dakwah digital harus bisa merevitalisasi pemahaman dan kesadaran esensi dan etika bermedia bagi umat, salah satunya dengan turut serta mensosialisasikan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial dengan dakwah-dakwah yang unik dan menarik.
Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akun medsos : @afahrur.rz